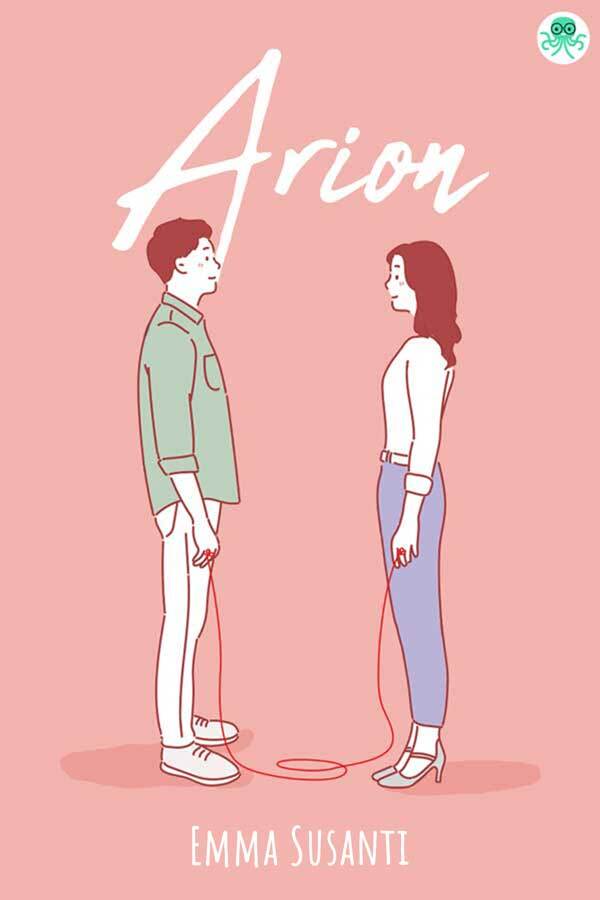
Arion
By Emma Susan
Manhattan, NYC, 03 Oktober 2017
Sembari merasakan dinginnya udara New York yang menembus mantel dan syalku, kusesap coffee latte di sebuah kafe yang berada di kawasan 5th Avenue. Kafe yang sudah beberapa tahun ini menjadi kafe favoritku. Sebenarnya tak ada yang spesial; rasa kopinya tak terlalu jauh berbeda dengan kafe-kafe lain yang pernah kudatangi. Hanya saja, kafe ini letaknya cukup dekat dari tempat tinggalku. Bahkan, hanya berbeda beberapa blok saja.
Baiklah, agak aneh memang mengingat meja yang kutempati sekarang. Alih-alih menempati bagian dalam kafe yang hangat, meski karena pemanas ruangan, aku malah menempati salah satu meja paling sudut di luar yang bersebelahan dengan trotoar. Musim dingin memang belum tiba tapi, temperatur kota akhir-akhir ini cukup rendah hingga membuatku harus mengenakan mantel ke mana-mana.
Jadi, alasanku bertahan di luar sini sambil menyesap minumanku adalah karena aku lebih suka bersantai sambil memperhatikan orang-orang yang berlalu-lalang di jalanan. Memang tak seindah lukisan-lukisan karya Van Gogh yang dipajang di museum seni di 11 West 53 Street itu—Joice yang bilang indah, karena sejujurnya aku tak terlalu mengerti juga tertarik pada lukisan. Namun, memperhatikan orang-orang di kala sendirian, entah kenapa malah membuatku merasa nyaman. Aku selalu merasa bisa menjernihkan pikiran di tengah-tengah keramaian.
Aku, Aria Darra Prameswari. Setelah lulus SMA di Jakarta, aku langsung pindah ke Manhattan, tempat di mana Jefri dan Monna—Om dan Tanteku—tinggal. Kemudian, aku meneruskan studiku di Parsons, the New School for Design dengan mengambil jurusan fashion design.
Ketertarikanku pada fashion berawal dari iseng-iseng membaca majalah terbitan New York yang Tante Monna kirimkan untuk Mama ketika aku masih SMA dan tinggal di Jakarta. Kebetulan majalahnya memang memuat berbagai macam hal tentang fashion. Aku begitu tertarik ketika menemukan halaman yang memuat pakaian-pakaian bertema “Monochrome”. Kagum akan nuansa hitam-putih yang bisa diterapkan di berbagai macam gaya busana juga pola: garis-garis, kotak-kotak, hingga pola bunga yang sering kutemukan dalam beberapa doodle art.
Setelah itu, aku mulai mencoba mendesain pakaian sendiri melalui gambar. Tak hanya monokrom, tapi aku juga mencoba memadupadankan desain-desain pakaianku dengan warna kromatik dan akromatik. Mengetahui hal itu, Mama menyarankanku untuk melanjutkan sekolah dengan jurusan Fashion Design. Bahkan semakin antusias ketika Tante Monna menawariku untuk tinggal bersamanya di New York.
“Kariermu akan cemerlang dengan menyandang status sebagai lulusan dari salah satu sekolah mode terbaik di dunia,” kata Tante Monna ketika aku bertukar pesan melalui surel dengannya.
Kepercayaanku semakin meningkat ketika Tante Monna—atas dasar temannya yang juga menggeluti bidang Fashion Design—berkata bahwa aku memiliki bakat, dan desain-desainku hampir layak dipertimbangkan. Ya, aku memang pernah mengirimkan beberapa gambar di kertas HVS-ku ke surel Tante Monna. Namun, aku tak menyangka ia akan memperlihatkannya pada seseorang yang memang ahlinya. Akhirnya, berbekal keyakinan dan dukungan yang sangat tinggi dari orang-orang terdekatku, aku pun terbang ke Amerika.
Empat tahun mengenyam bangku kuliah dan lulus, ditambah berhasil mendapatkan peringkat terbaik, aku pun mulai bekerja di sebuah perusahan ternama berada di kawasan yang juga menjadi area tempat tinggalku. Semua yang kulakukan memang tak lepas dari Manhattan. Bahkan, aku bertemu dengan “dia” pun, ya, di sini. Di Manhattan. Tepatnya, di Carnegie Hall.
“Pasti di sini.”
Ini dia. Pria yang kutemui di Carnegie Hall empat tahun lalu. Si rambut setengah pirang—sekarang begitu, karena pangkal rambutnya mulai ditumbuhi rambut-rambut baru berwarna hitam kecokelatan—yang wajahnya langsung merengut begitu berhadapan denganku. Siapa suruh dia membuatku menunggu selama hampir satu jam.
“Sengaja ya?” Sambil melepas syal di lehernya dia memicingkan mata.
Aku hanya tersenyum sambil menatapnya penuh kemenangan. Dia sangat benci dingin. Oleh sebab itu, selain memang senang memperhatikan orang-orang berlalu-lalang di jalanan, kupilih tempat di ruang terbuka seperti ini karena sekaligus ingin sedikit mengerjainya. Anggap saja sebagai hukuman.
“Enggak usah. Aku, kan sudah pakai,” tolakku begitu dia hendak melingkarkan syalnya ke leherku.
“Pakai saja,” katanya bersikeras, aku tak bisa menolak.
Sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangan dia duduk di hadapanku, kemudian menyambar coffee latte milikku. Lalu mengeluh setelah menyesapnya sedikit. “Dingin,” katanya.
“Masa? Baru mau satu jam masa sudah dingin?” ledekku.
“Oke, oke.” Dia menyerah. “Maaf karena sudah terlambat. Tapi—”
“Jangan mengatasnamakan manajermu,” selaku.
Wajahnya kembali merengut. “Aku tidak pernah mengatasnamakan Paul, tapi nyatanya, memang dia yang selalu menjadi alasanku terlambat bertemu denganmu. Dia yang menyusun jadwal, tapi dia sendiri juga yang mengacaukannya,” ujarnya sambil mengedikkan bahu.
Petra Surya Pratama. Pianis ternama dengan jadwal yang sangat padat. Bahkan, lebih padat daripada jadwalku sendiri. Sudah tiga tahun aku berkencan dengannya. Setelah berkenalan dan menjalin pertemanan selama satu tahun, kuputuskan untuk menerima cinta dan menjalin hubungan yang lebih serius lagi dengannya. Kenapa harus menunggu satu tahun sementara Petra telah beberapa kali memintaku menjadi kekasihnya? Entahlah. Aku hanya merasa tak yakin. Apalagi, sampai saat ini aku selalu merasa ada yang janggal dengan pertemuan pertama kami. Ditambah, sosoknya yang memang sedikit misterius bagiku. Kenapa demikian?
Pertama, ketika kami pertama kali bertemu. Saat itu, Joice si pencinta seni sekaligus sahabatku memintaku untuk menemaninya melihat resital piano yang diselenggarakan di Carnegie Hall. Jujur, selain lukisan aku pun tak tertarik pada musik. Apalagi musik klasik. Kukatakan pada Joice kalau dia salah memilih partner. Namun Joice tak peduli. Dia tetap memaksaku untuk menemaninya. Joice bilang kalau temannya yang baru saja debut yang akan bermain di atas panggung.
Sungguh! Joice tak pernah memberitahuku kalau ia punya teman seorang pianis.
Namun pada akhirnya, aku pun terpaksa mengiakan permintaannya. Oh, baiklah! Tidak terlalu terpaksa karena dia menyogokku dengan sepotong cheese cake terlezat di Manhattan.
Di sanalah untuk pertama kalinya aku bertemu Petra. Pianis yang katanya baru memulai saja debutnya sekaligus teman Joice.
***
Carnegie Hall, 4 tahun yang lalu
Kutunggu Joice yang sejak tadi tak keluar juga dari toilet sembari memainkan ponsel. Sebenarnya bukan memainkan tapi, mengecek kalau-kalau ada panggilan masuk yang tak terjawab. Seperti panggilan dari Tante Monna yang sudah sering kali terabaikan jika aku sedang berada di luar. Kadang aku memang tak sadar kalau ponselku berbunyi. Padahal deringnya selalu kusertai getar. Entahlah.
Oh, cepatlah, Joice! Gerutuku sambil terus memperhatikan jam.
Seharusnya dia sudah bisa mengubah kebiasaannya yang satu itu. Ya, kebiasaannya berlama-lama di toilet. Dalam kondisi tidak antre saja, Joice bisa menghabiskan waktunya di toilet selama lebih dari setengah jam. Itu pun hanya terdiri dari buang air kecil dan membereskan riasan. Apalagi jika ditambah kondisi toilet yang sedang kosong melompong, bisa sampai satu jam penuh dia berada di dalam sana.
Tak lagi sabar menunggu membuatku hendak menyusul Joice. Namun begitu tanganku sampai di pegangan pintu, seseorang menepuk bahuku dengan cukup keras. Aku tersentak. Tentu saja! Siapa yang tak akan terkejut, jika tiba-tiba ada seseorang yang seolah mencegahku masuk ke toilet? Namun, setelah kuperhatikan tanda yang berada tepat di atas pintu, aku semakin yakin kalau aku tidak akan salah masuk. Tandanya menunjukkan kalau pintu di depanku ini memang pintu masuk toilet khusus wanita.
“Aria.”
Belum sempat aku berbalik tapi, aku tahu kalau yang berada di belakangku sekarang adalah seorang pria. Namun, suaranya terdengar lemah. Berbanding terbalik dengan napasnya yang menderu hebat.
Siapa?
Kubalikkan tubuh dan menatapnya dari atas sampai bawah. Rambutnya pirang, kulitnya putih bersih dan wajahnya sangat oriental. Aku seperti mengenalnya tapi, juga tidak. Namun jika aku dan dia memang tak saling kenal, mengapa dia harus menatapku seperti itu? Tatapan yang sarat akan kesedihan.
“Excuse me?” Kuputuskan untuk bertanya saja.
Entah perasaanku saja atau bukan, tapi pertanyaanku sepertinya membuat pria itu sangat terkejut. Kedua netranya saja langsung membeliak. Namun, aku tak berbohong. Setelah kucari-cari lagi dalam ingatanku, dia memang tak ada di sana. Aku memang tidak mengenalnya.
“Sepertinya aku salah orang.” Dia kontan berbalik. Melangkah pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi.
Aku dibuat terkejut oleh fakta bahwa ternyata pria itu lancar berbahasa Indonesia. Atau mungkin, dia memang dari Indonesia sama sepertiku. Namun, bukan hanya karena itu. Satu hal yang lebih membuatku terkejut adalah, fakta bahwa tadi dia sempat dengan jelas menyebut namaku.
***
Setelah kejadian itu, dengan Joice sebagai perantara, aku pun berkenalan dengan Petra. Dari Joice pula aku tahu kalau saat itu, saat Petra tahu aku sahabat baik Joice, Petra bersikeras agar Joice memperkenalkanku padanya. Masih menjadi misteri bagaimana bisa Petra mengetahui namaku ketika pertemuan pertama kami di depan toilet. Namun kalau dipikir kembali, bisa saja Joice pernah secara tak sengaja menyebut namaku di depannya.
Oke, kemisteriusan Petra yang kedua adalah, dia tahu betul apa yang aku sukai. Padahal, sebelumnya aku tak pernah memberitahunya apa pun tentangku. Kebetulan? Kurasa tidak. Mana mungkin dia bisa mengetahui banyak hal tentangku sementara aku sendiri terkadang tidak sadar akan hal itu. Misalnya, ketika kami secara tak sengaja bertemu di minimarket. Tiba-tiba Petra mengatakan, “Pasti susu cokelat!” di saat aku benar-benar tengah menaruh tanganku di sekotak susu rasa cokelat yang terletak di dalam lemari pendingin. Hal yang bahkan tak kusadari sebelumnya bahwa aku memang selalu membeli susu rasa cokelat jika sedang mampir ke minimarket.
Ketiga, dia bahkan tahu warna kesukaanku adalah merah. Satu waktu ketika aku mengeluarkan dompet berwarna merah kesukaanku, Petra langsung berkata, “Sesuai dengan warna favorit kamu.” Padahal, dari semua benda yang kupakai saat itu, hanya dompet itulah satu-satunya benda yang mencirikan warna kesukaanku. Tebakan yang beruntung? Kurasa tidak begitu. Bagaimana bisa Petra langsung menyimpulkan bahwa merah adalah warna favoritku hanya dari satu benda saja? Bukankah itu aneh? Entah ia bisa meramal atau apa, yang jelas Petra memang sangat misterius.
Untuk sekarang, tepatnya setelah aku menerimanya menjadi pacar, aku tak ingin lagi memikirkan hal itu. Aku mau berada di sisinya karena dia memang membuatku merasa nyaman. Aku juga bisa merasakan cintanya yang tidak main-main untukku. Selain itu, dia juga sangat menggemaskan hingga tak jarang membuatku ingin menjailinya. Yang lebih penting dari itu, aku bahagia bersamanya.
Lagi pula kalau dipikir-pikir lagi sekarang, bisa saja Petra mengetahui segala hal tentangku dari Joice. Meski ketika kuinterogasi, Joice bersikeras tidak mengaku. Katanya, dia tak pernah memberi tahu Petra semua tentangku. Joice sendiri terkejut karena Petra terkadang menunjukkan sikap seolah-olah telah lama mengenalku. Apa aku percaya? Masa iya! Ha!
“Jadi, tetap mau di sini?” tanya Petra yang sepertinya sudah menggigil kedinginan.
Aku mendengus sekaligus menyembunyikan senyum di sudut bibirku. “Iya, iya,” ucapku sambil beranjak. “Kita ke dalam dan memesan sesuatu yang hangat untukmu.”
***
Udara di dalam memang lebih hangat, sekaligus lebih ramai. Tidak masalah jika aku dapat tempat duduk di dekat jendela di mana masih bisa memperhatikan jalanan. Sayangnya, semua tempat hampir penuh, kecuali sebuah meja dekat kasir di mana pegawainya lebih sering mengobrol ketimbang memperhatikan pelanggan.
“Semuanya sudah kamu persiapkan?” tanya Petra sebelum menyesap black coffee-nya. Warna kulitnya sekarang sudah tak sepucat tadi.
Aku mengangguk. “Barang-barang besar dan semua pakaian yang sepertinya nggak akan lagi aku pakai sudah aku kirim ke rumah minggu lalu.”
Petra mendenguskan napas berat. “Harusnya kamu tunggu aku tiga bulan lagi. Kita, kan, bisa pulang sama-sama,” keluhnya.
“Aku kan, sudah bilang nggak bisa. Fashion show-ku di Bandung kurang dari dua minggu lagi. Aku nggak bisa tunggu kamu menyelesaikan resital satu per satu.”
“Iya, sih. Tapi tetap saja aku kesal. Padahal aku kan, pengin ketemu calon mertua,” katanya dengan bibir mengerucut. Manis sekali.
Kuacak-acak rambut setengah pirangnya dengan gemas. “Kan, masih banyak kesempatan.”
Petra memang belum kupertemukan dengan kedua orang tuaku. Alasannya, karena memang belum ada waktu yang cocok untuk mempertemukan mereka. Tahun lalu, saat aku pulang ke Indonesia untuk berlibur selama dua minggu di sana, Petra tidak bisa ikut karena masih ada beberapa resital yang harus dikerjakan. Lalu, giliran Petra memiliki waktu luang untuk pulang ke Indonesia, aku yang tidak bisa karena tengah ikut berpartisipasi dalam ajang NYFW (New York Fashion Week).
“Pokoknya, setelah semua resitalku selesai dan aku punya waktu panjang untuk istirahat, aku akan langsung menyusulmu ke Jakarta. Aku akan menemui orangtuamu, lalu meminta mereka menyerahkanmu padaku,” ujar Petra sambil melipat kedua lengan di dada.
“Iya, iya,” kataku sambil tertawa.
Hubunganku dengan Petra memang sudah berlangsung cukup lama. Jadi, wajar jika kami ingin membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih jauh. Jenjang pernikahan.
Bicara tentang hubunganku dengan Petra, jujur saja aku sudah tak perlu lagi meragukan perasaannya terhadapku. Aku dan Petra sama-sama saling mencintai. Sama-sama saling mengerti dan memahami posisi satu sama lain. Kami juga sama-sama saling toleransi jika ada di antara kami yang sedang sibuk dengan pekerjaan atau hal lain. Bahkan, kami saling mendukung satu sama lain. Petra dengan pianonya dan aku dengan semua kesibukanku. Karena itulah, kami merasa tidak perlu menunggu lebih lama lagi hanya untuk memantapkan diri untuk menikah. Tentang niat Petra untuk mengatakan langsung kepada orangtuaku pun, meski dia tidak pernah mengatakan sebelumnya padaku, aku merasa setuju-setuju saja. Toh, memang sudah saatnya bagi kami untuk membina rumah tangga.
“Aku pasti akan sangat merindukanmu,” ucap Petra seraya meraih tanganku dan menggenggamnya erat.
“Aku juga, Honey,” balasku sembari menatapnya dan melakukan hal yang sama.
***
Aku sengaja mengambil penerbangan pukul 01.35 dini hari dengan satu kali transit agar bisa sampai ke Jakarta pada siang hari. Sebenarnya banyak penerbangan ke Jakarta pada siang hari, di jam-jam normal seperti pada pukul sebelas atau pukul dua belas siang. Namun, jika mengambil penerbangan pada jam-jam seperti itu, aku akan sampai di Jakarta pada malam hari, bahkan tengah malam. Tak akan ada waktu bagiku untuk bercengkerama bersama kedua orangtuaku karena sudah terlalu lelah menghabiskan waktu di perjalanan.
“Enggak ada yang ketinggalan?” tanya Tante Monna.
Aku menggeleng. “Enggak ada, Tan.”
“Jangan lupa sampaikan salam kami sama Mama dan Papamu,” ujar Om Jefri seraya menepuk lembut bahuku.
“Pasti, Om.”
“Kapan-kapan kami main ke Jakarta. Sudah lama juga nggak ke sana,” tambah Tante Monna sambil tersenyum.
Aku kembali mengangguk. Seingatku selama tinggal bersama Tante Monna dan Om Jefri, keduanya memang belum pernah lagi menginjakkan kakinya di Indonesia. Entah karena memang sibuk dengan pekerjaan, atau karena memang sudah betah tinggal di New York hingga lupa pada kampung halaman.
“Eh, iya! Pacar kamu mana?” tanya Om Jefri sembari melayangkan pandangannya ke segala arah.
“Aku larang dia datang,” jawabku sambil tersenyum tipis.
“Lho, kenapa?” tanya Tante Monna seraya mengernyit.
“Aku nggak mau istirahatnya terganggu, Tan. Nanti malam dia masih ada resital di Carnegie,” jelasku.
Kalau saja Petra tak ada resital, mungkin aku akan memintanya menemaniku setidaknya sampai aku masuk ke dalam pesawat. Aku tahu ini bukan perpisahan tapi, tetap saja menyedihkan ketika mengingat aku harus berjauhan dengannya selama beberapa bulan. Memang, di zaman canggih seperti sekarang kami bisa tetap mudah untuk berkomunikasi. Bahkan saling bertatap muka meski hanya bisa dilakukan lewat ponsel dan media sejenis. Namun, semua itu tetap saja tidak cukup. Lewat ponsel aku tak akan bisa mengacak-acak rambut atau mencubit pipinya ketika gemas. Oh, sungguh! Kekasihku itu memang sangatlah menggemaskan.
Speak of the devil. Ponsel di tanganku berdering. Sebuah panggilan video dari Petra menginterupsi pembicaraanku dengan Tante Monna dan Om Jefri. Kemarin malam Petra memang bilang mau menghubungiku setelah sampai di bandara.
Kutunjukkan ponsel di tanganku pada Tante Monna seraya berkata, “Petra.”
“Oh!”
Seolah mengerti maksudku, Tante Monna segera menarik Om Jefri sedikit menjauh dariku; memberi ruang untukku menerima panggilan dari Petra.
“Hai, Sayang!” sapaku begitu sosok Petra terpantul dari dalam layar ponsel.
“Aku nggak bisa tidur,” keluh Petra dengan wajah kusut. “Aku nggak mau kamu pergi,” tambahnya bernada merengek.
Di saat-saat seperti inilah aku ingin mengacak-acak rambutnya. Tak tahan melihat wajah merengut disertai rengekan manjanya.
“Ayolah! Kita kan, sudah bicarakan ini.”
“Tapi, tetap saja ....” Bibirnya semakin cemberut.
Kudenguskan napas panjang. “Begini saja,” kataku sambil berpikir. “Bagaimana kalau kita rencanakan liburan bersama pas kamu pulang ke Indonesia?”
Hanya rayuan yang mungkin bisa menghilangkan kekhawatirannya.
“Liburan?” tanyanya dengan sebelah alis terangkat.
Aku mengangguk mantap.
“Hanya kau dan aku?” Dia kembali bertanya seolah ingin memastikan.
“Tentu saja! Hanya kita berdua.” Memangnya kau mau mengajak Paul?
Kini Petra terdiam. Cukup lama sebelum dia berkata, “Baiklah! Kau berhasil membujukku, Aria.”
Aku terkekeh. Rayuan memang senjata paling ampuh untuk menenangkannya.
“Sampai sana jangan lupa kabari aku!”
“Pasti,” kataku.
“Hati-hati. Di pesawat nanti kamu langsung istirahat. Tidur!”
Aku kembali mengangguk. “Kamu juga. Habis ini harus langsung tidur. Masih ada resital, kan?”
Giliran Petra mengangguk. “Iya. Aku juga sudah mengantuk sekarang.”
“Oke. Kayaknya sudah waktunya,” kataku sambil melirik jam. “Nanti aku kabari lagi kalau sudah sampai Jakarta.”
“Hei, Aria!” panggil Petra sebelum aku berniat memutuskan panggilanku. “Jaga hatimu, ya,” ujarnya seraya tersenyum.
Aku membalas senyumannya dan menjawab, “Pasti. Kamu juga.”
“Tentu saja,” pungkasnya sebelum sosoknya benar-benar menghilang dari layar ponsel.
Ada-ada saja. “Jaga hatimu”, memangnya dia pikir hatiku ini untuk siapa kalau bukan untuknya? Terkadang aku merasa kekhawatirannya itu terlalu berlebihan. Akan tetapi tak mengapa. Bukankah itu tandanya Petra benar-benar tak ingin kehilanganku?
***