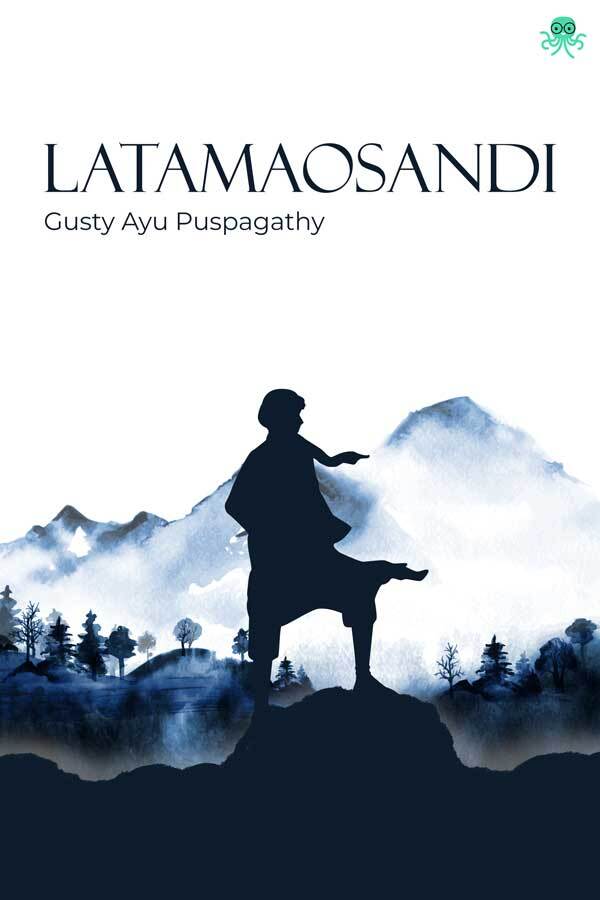
Latamaosandi
By G.A. Puspagathy
Ketidakhadiran matahari dua minggu belakangan ini cukup membuat warga kabuyutan Gogik resah. Mendung yang berkepanjangan bukanlah pertanda yang baik.
“Semalam aku dengar desa sebelah diserang oleh kawanan penyamun, untungnya tidak ada korban jiwa satu pun.”
Masih tak ada sahutan dari lawan bicaranya meskipun berulang kali Saniscara mengganti topik. Dia pun kembali memilah ratusan buah mangga yang harumnya memabukkan seisi rumah. Begitu menemukan satu yang busuk, dia lempar tepat ke wajah pemuda yang sejak tadi serupa arca, mematung dan tenggelam dalam kitab usang yang dibacanya.
“Ambilkan satu yang bagus untukku.” Pemuda itu pun baru angkat bicara saat berhasil menangkap mangga busuk.
“Yang itu cukup untukmu, Kakang. Yang ini akan kujual.”
“Kamu tak akan rugi jika memberiku satu yang paling harum.”
Saniscara melempar buntalan berisi mangga yang telah disisihkan. Barulah Bhanu beranjak dari duduknya untuk menangkap buntalan itu. Dia tersenyum masam saat melihat isinya.
“Lalat pun tahu buah-buah ini telah busuk.”
Saniscara tak peduli. Dia kembali memasukkan mangga yang layak ke dalam karung. Di antaranya, diselipkan pesanan khusus dari pelanggannya. Perhiasan, selendang, belati, kain, tembikar aneka rupa hingga ramuan obat sesuai permintaan, dipisahkan dalam beberapa karung berbeda dan ditutupi dengan mangga. Saniscara tak pernah mengecewakan pelanggan yang sudah memberikan denyut kehidupan keluarga kecilnya.
“Akan kamu jual ke mana buah-buah itu?”
“Inggu.”
“Katamu semalam ada serangan dari para penyamun, apa tidak lebih baik kamu menunda perjalananmu dulu?”
“Dan membiarkan buah-buah ini membusuk? Tidak, terima kasih, Kakang.”
“Jual saja di sini. Dua hari perjalanan ke Inggu dalam kondisi seperti ini justru berbahaya. Bagaimana jika penyamun itu adalah anak buah Mangkara yang mencari mangsa?”
Diam-diam Saniscara bahagia sebab masih ada kekhawatiran di mata Bhanu. Jika bisa memilih, tentu lebih baik dia di rumah merawat ibunya. Namun, Saniscara tak cukup mampu untuk membuat segala macam ramuan untuk mempertahankan napas ibu. Hanya Bhanu yang bisa. Dan dedaunan dari alas dekat rumahnya belum mencukupi kebutuhan. Masih ada bahan yang harus ditukar dengan keping-keping tembaga.
“Mungkin ini akan membuatmu lebih tenang, Kakang. Aku berangkat bersama Dipa.”
Mendengar nama itu, Bhanu mendekat dan berjongkok di sebelah Saniscara. Sudah lama dia tidak bertemu sahabatnya. Kemari pun dia hanya meninggalkan barang-barang di belakang rumah. Barang pesanan yang akan dijualkan adiknya.
“Kenapa dia tidak datang menjemputmu?” Bhanu mengecilkan suara.
“Kenapa harus? Dia menungguku di perbatasan desa petang nanti. Aku sudah terlalu tua untuk dijemput. Memangnya aku ini kekasih atau istrinya?”
“Tetap saja itu tidak sopan.” Bhanu tidak mengerti kenapa adiknya tersipu. Dia lebih tertarik dengan hal lain daripada pipi Saniscara yang merona. “Jangan-jangan yang semalam itu ....”
“Bukan, bukan. Dia tidak terlibat,” sergah Saniscara buru-buru. Tahu apa yang ada di pikiran Bhanu. “Harusnya Kakang lebih mengenalnya. Dia selama ini bekerja sendiri.”
Bhanu tahu sahabatnya itu hanya merampok rombongan orang kaya yang sedang sial. Wilayah perburuannya pun jauh dari kabuyutan Gogik. Tetapi dalam kondisi paceklik seperti ini, kemungkinan dia melancarkan aksinya di sekitar sini tak mustahil sama sekali.
“Kamu merindukannya, Kakang? Akan kusampaikan nanti.” Saniscara menggoda kakangnya yang kembali memegang kitab. “Bantu aku dulu menaikkan barang-barang ini ke pedati atau kusobek kitab itu. Aku mau berangkat.”
Lima karung telah mengisi pedati. Lembu putih menjadi satu-satunya kawan perjalanan Saniscara selama setengah hari perjalanan ke perbatasan desa tempat dia akan bertemu Dipa. Bhanu melepas kepergian adiknya dengan waswas. Harusnya dia membiarkan Saniscara menghabiskan masa kecilnya bermain dengan teman sebayanya atau paling tidak melewatkan masa remajanya kini dengan mengandai-andai dipinang saudagar kaya seperti gadis-gadis lain. Namun, keadaan memaksa mereka hidup untuk bertahan di tengah huru-hara.
Bhanu kembali ke dalam rumah, memasuki satu-satunya kamar yang sudah menjaga ibunya selama sepuluh tahun dalam keadaan sekarat. Daging wanita paruh baya itu telah digerogoti waktu. Napasnya masih bertahan. Namun matanya tak kunjung terbuka.
Puluhan kitab pengobatan telah Bhanu pelajari. Berbagai ramuan telah dia coba. Entah sudah berapa tabib yang sudah dia panggil, tak ada satu pun yang tahu penyakit apa yang menimpa ibunya. Bhanu mengambil gelas yang telah disiapkan adiknya di sisi ranjang. Pemuda itu menegakkan kepala sang ibu di depan dadanya. Dia mulai memasukkan makanan yang telah dibuat secair mungkin agar mudah ditelan ibunya.
“Saniscara baru saja berangkat ke Inggu, Ibu. Semoga Dewata melindunginya. Andai Ibu membuka mata sedikit saja, Ibu akan lihat dia bukan lagi anak tujuh tahun yang selalu merengek minta gendong,” cerita Bhanu.
Ibu masih bisa mendengar kita, jadi tumpahkan cerita apa saja pada Ibu agar dia tahu kita tak pernah meninggalkannya, begitu pinta Saniscara pada Bhanu tiap kali dia pergi meninggalkan rumah. Dan begitulah yang selalu dilakukan Bhanu.
Dengan hati-hati, Bhanu meletakkan kembali kepala ibunya setelah menyuapi. Ada kedamaian dalam raut muka perempuan itu, tapi tidak di wajah Bhanu.
“Aku segera kembali sebelum petang, Ibu. Ada yang harus ditukar dengan berkeping-keping tembaga.”
Kelewang, jerat tali dan sumpit beracun telah Bhanu siapkan dalam keranjang bambu yang telah ditutupi dedaunan dan umbi-umbian. Keranjang itu bertengger manis di punggung Bhanu, menemani perjalanannya menuju alas yang diwingitkan penduduk sekitar.
***
Kabut malam ini menambah sunyi suasana di kabuyutan Gogik. Api dalam suluh bambu yang menempel di tiang emper maupun di pagar rumah penduduk, sama sekali tak mampu memberi penerangan. Saat seperti inilah, kelengahan penduduk dimanfaatkan.
Beberapa pria dewasa bernyali, tampak berkeliling. Berita tentang penyerangan desa tetangga tentu sudah menyebar luas. Mereka tak mau peristiwa itu juga terjadi di dukuh kecil ini.
Bhanu belum tidur ketika mendengar percakapan para peronda yang melewati rumahnya. Asap daging kobra dengan wangi rempah menemani Bhanu yang sedang meracik bisa, darah dan empedu kobra buruannya menjadi bubuk obat. Sebagian dia sisihkan untuk persediaan ibunya, sisanya untuk mengobati orang-orang yang datang padanya.
Keadaan senyap kembali ketika para peronda itu pergi. Hingga Bhanu mampu mendengar langkah berat di atap rumah. Kelewang yang tergantung di dinding dia genggam erat. Kantong yang tergantung di pinggangnya pun telah dia isi. Bergegas dia ke kamar ibunya untuk memastikan jendela sudah terkunci. Pendengaran terus dia tajamkan.
Selang sepeminuman teh, terdengar teriakan dan suara kentongan bersahutan. Isyarat yang dipukulkan menandakan ada penyerangan atau perampokan. Rasa ingin tahu membuat Bhanu membuka sedikit jendela untuk melihat situasi di luar. Beberapa pria dewasa yang sebelumnya berpatroli di sekitar rumah Bhanu berlarian menuju ke sumber suara. Pikiran Bhanu justru membayangkan keselamatan adiknya saat ini.
“Dia bersama Dipa. Aku yakin mereka bisa menjaga diri,” katanya menenangkan diri.
Tepat saat Bhanu merasa semua sudah aman dan tak terdengar lagi keributan di luar sana, telinganya menangkap suara mencurigakan dari arah dapur. Dengan mengendap-endap, Bhanu memberanikan diri memeriksanya. Sebuah pisau meluncur ke arahnya. Beruntung Bhanu dapat menepisnya dengan kelewang.
“Maling atau genderuwo, siapa pun kisanak, aku perintahkan untuk keluar dari sini. Kami tidak memiliki barang berharga yang bisa kau ambil.”
Sosok bertopeng itu muncul dari sudut ruangan. Pakaiannya yang serba hitam membuatnya mudah berbaur dengan kegelapan. Tanpa pikir panjang, Bhanu langsung melepaskan serangan. Kelewang yang dia genggam terpental. Giliran tendangan dilancarkannya sambil melompat. Sosok itu melentingkan tubuhnya jauh ke belakang. Dilihat dari kelincahannya, orang itu jelas-jelas memiliki ilmu silat yang tinggi. Bhanu menyusul. Kali ini dia mengirimkan tinju yang menyasar ke dada. Lagi-lagi serangan itu bisa dihindari. Tinjunya hanya bertemu udara kosong. Bhanu merasakan ada yang aneh dengan sosok itu. Dia telah menyerangnya berkali-kali namun tidak pernah mendapat balasan.
Jangan-jangan orang ini meremehkanku, batinnya.
Tanpa memedulikan hal itu, Bhanu mengambil kembali kelewangnya serta pisau terdekat, lantas memasang kuda-kuda lebih rendah. Kelewang siap membabat, pisau siap menusuk. Matanya awas memperhatikan gerak-gerik musuh, telinganya tajam menangkap setiap pergerakan. Dia mengingat setiap latihannya bersama Dipa dan mendapatkan sebuah gagasan.
“Posisi itu .... Sundang Maospait,” gumam si sosok bertopeng.
“Oh, kau bisa bicara juga ternyata,” ledek Bhanu. ”Tentu kau tahu kalau saat ini aku tidak main-main lagi.”
Bhanu memang belum mempelajari jurus itu dengan sempurna, tapi saat ini dia tidak punya pilihan lain. Dia telah membulatkan tekad untuk mengeluarkan salah satu jurus penyerangan dari Sundang Maospait. Serangan demi serangan membuat lawannya terdesak. Tetapi tak ada niatan musuh di hadapannya ini untuk kabur. Tebasan Bhanu hanya mampu mencompang-campingkan pakaian musuh. Ketika lengan kanan baju musuhnya tersibak, tahulah Bhanu jika lawannya telah terluka sebelum bertamu kemari. Ini sebabnya dia tak memberi perlawanan.
Di saat Bhanu lengah menatap luka itu, tendangan musuh telah menjatuhkan semua senjata Bhanu. Pemuda itu membalas dengan pertarungan tangan kosong. Ketika pertahanan tubuh bagian depan musuh lengah, Bhanu memiringkan tubuh dan langsung menyikutnya tepat di ulu hati. Serangannya terbaca. Lengan kanannya tertangkap.
“Jurus milikmu masih payah. Seharusnya kau menggunakan kepalan tanganmu untuk serangan pamungkas, bukan siku,” ujar tamu tak diundang tersebut.
“Aku tahu,” balas Bhanu.
Bhanu tersenyum. Segera tangan kirinya menarik kantong yang menggantung di pinggang dan melempar tepat ke muka lawannya. Serbuk kuning merebak ke udara. Bhanu menahan napas beberapa detik sampai musuhnya melepas tangan kanan Bhanu. Meskipun sudah menghindar, Bhanu yakin lawannya itu telah menghirup serbuk racun buatannya dengan jumlah yang tidak sedikit. Jumlah yang cukup untuk membuat siapa pun tidak sadarkan diri.
“Kurang ajar! Apa yang kau lakukan? Benda apa itu tadi?” Sosok itu masih siaga walaupun terlihat agak sempoyongan.
“Aku akan memberitahukannya padamu besok pagi, beristirahatlah,”
Persis seperti yang dikatakan Bhanu, sosok itu ambruk. Bhanu menyalakan lampu semprong dan mendekat. Kondisi lawannya itu mengerikan. Darah membasahi pakaiannya dan bahkan masih belum berhenti mengalir. Itu bukan luka karena serangan Bhanu. Dia menyadari bahwa sosok itu telah menderita luka yang serius sebelum bertarung dengannya. Sebagai tuan rumah, dia berhak mengadili siapa pun yang menyusup ke tempatnya, tetapi nalurinya tidak bisa membiarkan seorang manusia menderita, penjahat sekalipun. Bhanu harus menyelamatkan nyawa yang tergolek tanpa daya di depannya. Topeng penutup wajah itu pun dibuka. Dibaliknya ada sosok ayu yang meringis menahan sakit.
***