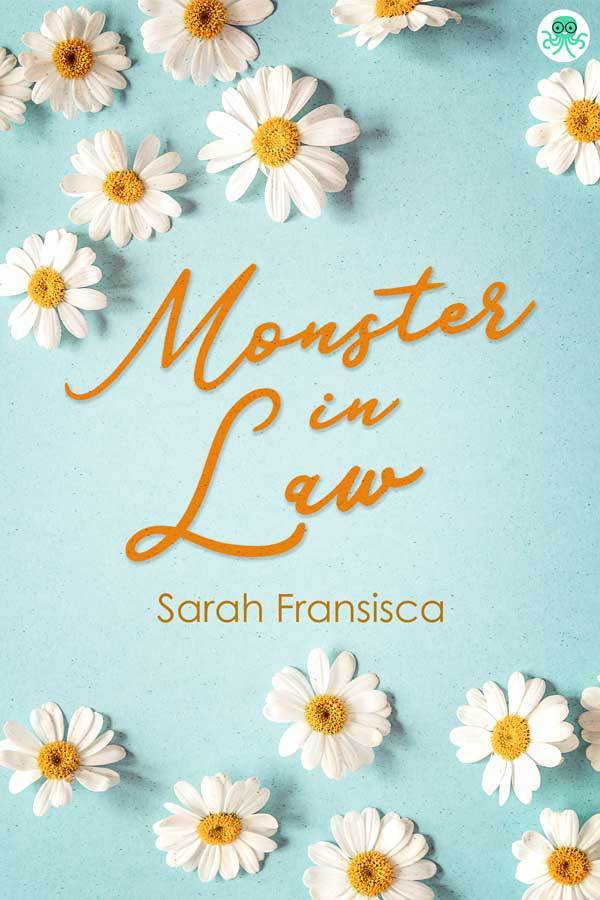
Monster In Law
By sarah fransisca
Jakarta, 30 November
Aku menghela napas pelan sambil memejamkan mata, berusaha keras agar tidak memijit pelipisku yang terasa begitu berdenyut. Nyaris setengah jam aku menguatkan diri agar tetap terlihat anggun dan seolah tidak terpengaruh omongan-omongan yang menyakitkan itu.
“Dengar, Flo, kalau kamu tidak bisa memberi anakku keturunan, jangan egois. Biarkan dia bersama wanita yang terbukti bisa memberinya anak.” Suara itu kembali dengan efek mematikan lebih hebat dari sebelumnya.
“Bisakah Mama tidak hanya melihat kekuranganku?” tanyaku dengan perasaan lelah luar biasa. Tidak ada amarah dalam nada suaraku meski rasanya aku ingin menghancurkan gunung saat ini juga.
Mama menatapku seolah aku adalah sampah yang sangat ingin dia singkirkan. “Seharusnya kamu bisa sadar diri tanpa harus mama jelaskan perbedaan kamu dengan wanita yang mama jodohkan dengan suamimu, kan?” Mama tersenyum selayaknya menertawakan semua kekuranganku. “Kamu bukan hanya tidak bisa memberikan anak, kamu juga tidak bisa menjadi penolong bagi suamimu.” Mama menjeda kalimatnya demi memenuhi paru-parunya dengan oksigen baru. “Untuk apa menantu tukang kebun yang tidak mampu memberiku cucu, kalau aku bisa punya menantu pebisnis kaya dan mampu melahirkan bayi-bayi menggemaskan?”
Apa ada hal paling menyakitkan lagi dibandingkan mendengar perkataan yang begitu jahat dari mulut wanita yang seharusnya menganggapku seperti anaknya sendiri?
Aku memiringkan kepala untuk menatap lebih jelas iris mata wanita paruh baya berdarah Sunda di hadapanku ini. Kusunggingkan senyuman demi menutupi perasaanku yang babak belur. “Maaf, sebenarnya aku tidak pernah berniat untuk mengungkit apa yang sudah kuberikan, tapi pernahkah sebelum berkata seperti itu Mama berpikir sedikit saja, bahwa jika bukan karena hasil tukang kebun ini.” Kutunjuk dadaku dengan telunjuk kanan demi memperjelas. “Kalau bukan karena gaji berkebunku, Mama tidak mungkin bisa melanjutkan terapi dan merasakan kembali berjalan dengan kedua kaki Mama?”
Aku menarik napas dalam menikmati setiap detik perubahan raut wajah Mama, setiap detail ekspresi terkejutnya. “Pernahkah Mama berpikir, mungkinkah calon menantu yang Mama banggakan itu mau menggantikan tugas kedua tangan dari orang yang paling Mama benci di dunia untuk merawat Mama selama ini?”
Mama terdiam seolah suaranya tertelan kembali. Namun sedetik kemudian dia kembali mendapatkan keangkuhannya. “Semua itu tidak ada artinya jika tanpa hal paling penting, Flo,” katanya dengan nada dingin. “Tidak ada artinya,” ulang Mama sambil berjalan meninggalkan ruang keluarga.
Setelah Mama menghilang di balik pintu kamarnya, aku menjatuhkan bokong ke sofa. Kakiku yang sejak tadi kupaksa tetap berdiri tegak, kini kehilangan tenaga dan berubah menjadi selembek agar-agar. Bongkahan air mata kembali menghajar pertahananku seperti gelombang tsunami. Meski sanggup menahan isakan, nyatanya aku gagal membendung lelehan di kedua pipiku. Aku berusaha mengatur napas demi menghentikan laju air mata. Sayangnya berkali-kali kucoba menarik napas sedalam apa pun tetap tidak mampu menghentikannya. Aku menyerah melawan sayatan di dada dan memilih untuk kembali ke kamar tidur.
Aku menjatuhkan diri di atas tempat tidur, membenamkan wajah di bantal, melepaskan isakan yang sejak tadi kutahan sekuat yang kumampu. Tidak apa-apa, Flo, menangislah sebelum kembali membohongi dunia kalau aku baik-baik saja. Tidak apa-apa kalau sekali ini aku mengakui bahwa aku tidak baik-baik saja dan aku hanya manusia biasa. Menangislah, Flo, habiskan air matamu hingga tidak ada lagi tangis yang bisa mereka lihat.
***