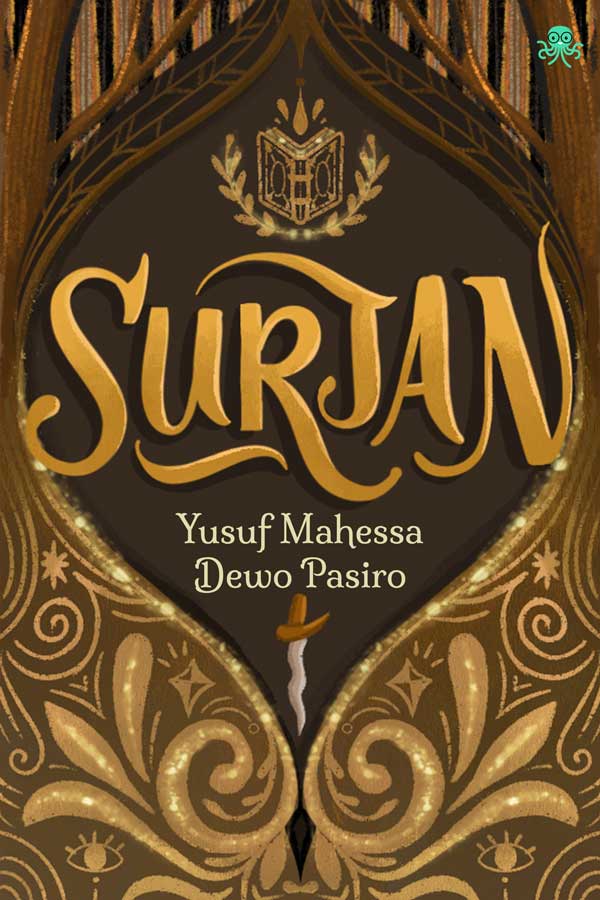
SURJAN
By dewopasiro
Aku tak tahu masa depan akan seperti apa, bagaimana aku tumbuh, seperti apa kehidupanku, bagaimana aku mati, dan siapa yang akan melayat. Saat ini diriku tak peduli dengan kejadian mendatang. Sekarang hanya ada rasa kesal yang menggumpal seperti bongkahan es di dada, kesal pada ayah dan ibu yang terus-terusan pindah rumah.
Sekolahku berantakan sejak enam semester lalu. Sudah tiga kali keluarga kami pindah rumah. Sekarang tepat saat umurku sepuluh tahun, kami pindah tempat tinggal lagi, kali ini di tanah kelahiran ayahku. Biarlah urusan kepindahan sekolah dan lain-lain jadi tanggung jawab ayah. Sudah dua minggu kami menetap di desa sunyi ini. Jarak rumah antar tetangga terpaut sangat jauh. Bahkan, rumah di seberang jalan jaraknya sekitar dua ratus meter. Sepertinya rumah tersebut yang paling besar di antara bangunan lain di desa ini. Fasadnya seperti kastil tua, jendela yang berkaca bening dan tak bertirai memandang angkuh ke halaman rumah kami, temboknya kokoh bercat putih tulang. Bangunan itu seperti rumah bergaya Eropa di film vampir.
Rumah yang sekarang kami tinggali adalah warisan kakekku. Beliau menyerahkan segala sertifikat tanah dan sebagainya kepada ayahku, karena memang ayah satu-satunya anak kakek. Awal kedatangan di rumah ini terasa biasa saja, tak ada yang menarik bagiku. Namun, dua hari berikutnya aku menjumpai hal yang tak biasa. Rumah besar di seberang jalan, rupanya milik keluarga blasteran. Mereka memiliki anak laki-laki berwajah pucat, kurasa memiliki darah campuran Eropa, kulit putih kemerahan, dan bermata biru seperti langit cerah di siang hari. Ibu anak laki-laki tersebut asli pribumi, ayah mereka mungkin yang keturunan Eropa—aku tak tahu pasti.
Tatkala aku duduk di kursi bambu yang berada di teras sambil memangku boneka panda hadiah ulang tahun dari ibuku, tak sengaja diriku melihat aktivitas di pelataran rumah besar di seberang jalan. Mataku memicing agar lebih fokus, kesan pertama yang kudapat dari aktivitas keluarga itu sungguh membuat bulu roman tegak berdiri seperti ditarik magnet. Sang ayah—berkulit putih dan berbadan besar tengah asyik duduk di kursi goyang sambil menisik sebuah baju, sepertinya sobek. Tampak anak laki-laki mereka yang kurasa berusia sepantar denganku, tengah bersimpuh di tanah. Si ibu berdiri di belakang anak laki-laki tersebut, tangannya memegang rotan—entahlah, mungkin bilah bambu. Wanita itu terus mengayunkan rotan ke punggung si anak laki-laki. Berkali-kali, hingga tangisan bocah tersebut terdengar sampai tempatku duduk.
Aku tak kuat melihat pemandangan mengerikan tersebut, buru-buru bangkit dari kursi dan berlari masuk ke rumah. Aku menutup pintu rapat-rapat, napasku terasa berat. Kenapa ibunya sangat kasar? Sungguh mengerikan, kasihan bocah laki-laki itu. Jelas, aku tak tahu-menahu tentang kesalahan anak laki-laki tersebut, mungkin saja ia memecahkan vas, tak mau makan siang, atau habis mencuri uang dan digunakan untuk membeli jajanan?
***
Minggu pagi tampak bersahabat, langit cerah tak berawan. Setelah kemarin melihat kejadian mengerikan di rumah besar, hari ini aku menjadi lebih was-was dan tak berani menatap rumah tersebut. Entah pagi ini kulalui penuh sukacita ataukah mungkin akan ada kejadian mengejutkan—ah, andai saja ada hujan uang, hujan cokelat, ataupun hujan ceri. Terlalu lama memikirkan hal tak pasti, aku pun memutuskan untuk menyirami tanaman bunga yang ada di depan rumah. Aku mengambil embrat dari gudang lalu mengisinya dengan air. Air membuncah dari lubang-lubang kecil ujung gembor saat kumiringkan. Bunga-bunga tampak segar, ada beberapa mawar yang belum mekar. Aku berjongkok untuk mencabut rumput kecil yang mengganggu.
“Hai!” suara seseorang mengejutkanku.
Aku meletakkan gembor di samping pot warna hijau, lantas perlahan berdiri dan membalikkan badan. Rupanya bocah laki-laki yang kemarin dihukum ibunya. Ia kini berdiri berhadapan denganku, tubuhnya lebih tinggi dari yang kubayangkan. Ia mengulurkan tangan kanan. “Aku Toni, rumahku di seberang jalan itu,” tangan kirinya menunjuk rumahnya.
Sejenak aku mengerjap tak percaya, masih ada keraguan, apakah akan menerima ajakannya untuk bersalaman atau tidak—kepalang tanggung, aku sudah tersihir oleh ketampanan Toni dan buru-buru kuterima uluran tangannya, kami berjabat tangan seperti orang tua yang baru saja menyetujui sebuah bisnis. “Namaku Ratih. Salam kenal,” ucapku.
Masih cukup canggung, sebelum Toni berbicara kembali, ia sejenak manarik napas. “Boleh?” ucapnya.
“Ah. Ya. Silakan duduk.” Aku mempersilakan dirinya agar duduk di beranda rumah. Kami berdua duduk di kursi bambu. Bocah laki-laki bernama Toni tersebut memandangi rumahnya—cukup lama dan tak berkedip.
“Hei. Mengapa kau melamun?” tanyaku. Mata Toni benar-benar biru cerah.
“Ah! Tidak.” Ia mengerjap dan melontarkan pandangan ke arahku, “maaf mengganggu aktivitasmu. Aku beruntung karena bisa keluar dari rumah. Kebetulan kedua orang tuaku sedang pergi ke kebun yang berada cukup jauh dari sini.”
Sepertinya ia memang merasa lega. Perangai bocah laki-laki tersebut cukup meneduhkan, suaranya sangat khas, ia juga memiliki wajah yang menyenangkan. Hidungnya panjang seperti paruh burung beo, lebih mancung dariku. Benar saja, aku ini memiliki hidung pesek, lagi pula aku bukan keturunan orang luar negeri.
“Tenanglah, kau sama sekali tidak mengganggu. Aku sudah selesai menyirami tanaman.”
“Baiklah. Mungkin aku hanya bisa di sini sekitar lima belas menit saja, takut kalau orang tuaku tiba-tiba pulang.”
Percakapan kami terasa lancar tak ada canggung sedikit pun, seolah-olah kami telah saling kenal cukup lama. Namun, ada yang ganjil, mengapa Toni terlihat lega sekali, apa ia jarang keluar—maksudku tak pernah main di luar rumah?
Spontan aku melontarkan pertanyaan yang mungkin akan menyinggung perasaan bocah laki-laki itu, “Apa kau tidak pernah main? Kenapa takut dengan orang tuamu? Aku kemarin tak sengaja melihatmu dihukum—dihukum ibumu.” Kalimatku tersekat di tenggorokan. “Maaf, mungkin dia adikmu, bisa saja aku salah lihat.”
“Tidak, aku memang tak pernah main di luar rumah. Aku tak punya adik, kau melihat sebuah kebenaran, memang diriku yang dihukum. Karena aku ingin bermain dan tak mau membaca buku.” Suaranya bergetar.
“Tak boleh main?” aku menatap wajah Toni. “Buku? Membaca buku apa, kenapa kau tak mau membaca?”
Ia menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskan dengan cepat. “Aku sudah jenuh membaca banyak buku, tetapi orang tuaku selalu keras dan melarangku untuk main. Aku hanya diperbolehkan membaca buku, sekarang harus membaca buku selama delapan jam sehari.”
Aku tak menyangka ternyata ada keluarga yang sangat keras, apa mereka ingin Toni menjadi mesin cerdas dan harus melahap semua buku-buku? Bocah blasteran tersebut mengusap wajah dan berdiri.
“Itu waktu yang sangat banyak untuk membaca, harusnya kau juga boleh main,” ucapku.
Toni menatapku, ia mundur tiga langkah dan bersandar pada teras. “Seharusnya begitu. Namun, sekarang sudah berbeda, dahulu saat aku masih tujuh tahun, hanya satu jam saja untuk membaca buku. Namun, sekarang ayah dan ibuku makin ketat dan memberi waktu membaca yang sangat banyak. Baru sekarang aku bisa keluar karena melihatmu di rumah ini. Semenjak dahulu aku tak boleh sekolah di luar rumah. Orang tuaku memanggil guru khusus dan harus mengajari, mendidik, membimbingku di rumah. Kau gadis pertama yang kutemui dan kuajak bicara selain Ibu—bahkan aku jarang bicara dengan ibuku.” Ia tampak lesu.
“Benarkah? Berarti kau mempunyai banyak buku di rumah?” Aku seolah kehilangan simpati dan justru menanyakan jumlah buku yang ia miliki.
“Ya, ada banyak. Ruang baca juga sangat besar, aku tak boleh keluar jika waktu membaca tiba. Ah! Berhubung kau sudah berbaik hati mau bicara denganku, maka akan kuajak kau ke dalam ruang baca di rumah. Aku ingin memiliki teman, tetapi diam-diam. Aku pastikan kau aman dan bisa membaca bersamaku.” Toni tampak semringah.
“Aku mau, sih. Banyak buku yang belum kubaca. Aku tak menyangka kau sudah jago membaca sejak usia tujuh tahun. Berapa buku yang sudah selesai kau baca?”
“Ya. Karena budaya keras di keluarga kami sejak masa eyang buyutku. Ayahku juga dahulu tak pernah keluar dari ruang baca tersebut. Sekarang aku sudah kelas enam sekolah dasar. Jika dihitung semenjak usia tujuh tahun sampai sekarang, kurasa aku sudah membaca lebih dari tujuh ribu sembilan ratus buku.”
Mulutku terbabang, mataku melotot nyaris melompat. Gila! Pencapaian yang sangat gemilang bagi Toni.
“Jadi sekarang kau berusia dua belas tahun? Mengagumkan, aku tak menyangka banyak buku yang telah kau baca. Apakah ruang baca yang kau bicarakan benar-benar banyak bukunya?” Aku sekali lagi memastikan banyak buku yang ia miliki, aku jadi merasa seperti orang idiot, berhadapan dengan kutu buku dan pastinya ia lebih cerdas dariku yang masih bau kencur.
“Ya. Aku dua belas tahun. Sedangkan kau pasti masih berumur sepuluh tahun, ‘kan? Kerutan kelopak matamu, tinggi badanmu, suaramu, serta caramu berbicara bisa membantuku menebaknya. Kau masih kelas empat sekolah dasar sekarang.” Ia terkekeh. “Benar, banyak buku di ruang baca, ribuan—tidak—puluhan ribu. Karena ruanganya sangat besar, nyaris sepuluh kali lipat ruang keluarga.”
“Hebat sekali kau bisa menebak usiaku dengan tepat. Bisa kubayangkan, rumahmu saja sebesar itu,” sahutku. “Baiklah. Kapan kau bisa mengajakku untuk masuk ruang bacamu? Apakah ada buku bergambar yang menarik? Lalu buku apa saja yang telah kau baca?” tanyaku polos.
“Besok pagi aku akan ke sini, orang tuaku pasti akan kembali berkebun. Akan kubawa kau masuk ke ruang baca bersamaku. Tenanglah, banyak buku di sana, bergambar, buram, berdebu, berlubang, semua ada. Buku filsafat, matematika, ilmu alam, mitologi, semua tentang astronomi, sejarah, sangat lengkap. Buku detektif, buku komedi, bahkan buku primbon juga ada. Terima kasih karena telah mau menerima ajakanku. Aku pamit, sampai jumpa besok.”
Toni bergegas lari menuju rumahnya. Aku memandangi punggungnya yang makin mengecil, lalu menghilang di balik pintu depan rumahnya yang sangat besar. Aku masih tertegun, sulit untuk memercayai ada bocah seperti dia. Baru saja ia menyebutkan berbagai jenis buku seperti buku Sejarah, Matematika, Filsafat, apakah bacaan seberat itu yang ia baca selama ini? Rasanya kepalaku berputar-putar tak karuan memikirkan Toni dan buku-bukunya.
Ia benar-benar memiliki daya tarik tersendiri. Buku jenis apa yang ia baca sehingga bisa menebak usiaku dengan tepat? Ah! Sekarang justru pikiran negatif terlintas di kepala, bagaimana kalau Toni orang jahat? Aku baru saja kenal dengannya. Harus bagaimana ini, aku telah terlanjur menyanggupi ajakannya untuk masuk ruang baca miliknya. []