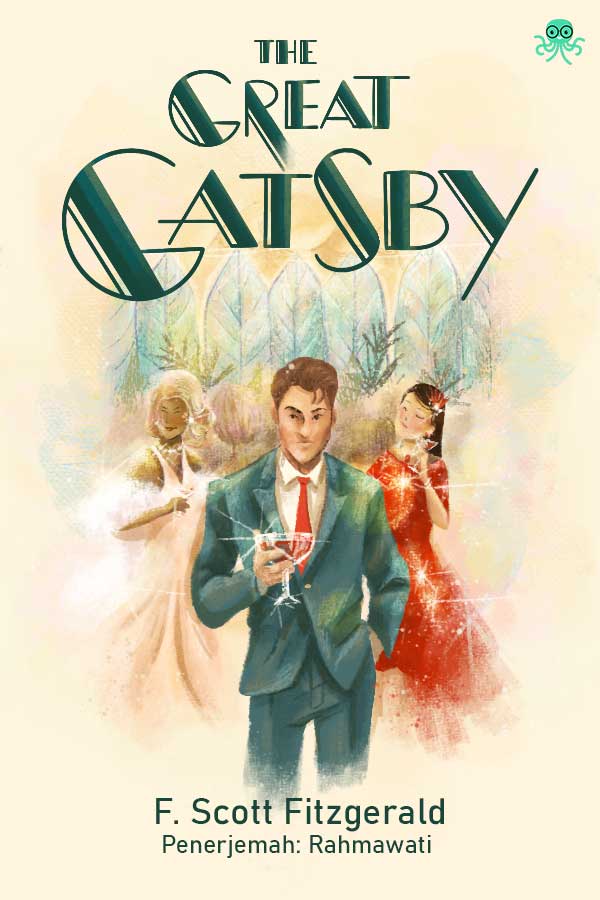
The Great Gatsby
By rahmachan
Sekali lagi,
untuk Zelda
Maka kenakanlah topi emas itu, jika itu dapat menggugahnya;
Jika kau dapat melambung, melambunglah untuknya juga,
Sampai ia memekik, "Kasih, kekasih bertopi emas, yang melambung tinggi,
aku harus memilikimu!"
Thomas Parke d’Invilliers
I
Ketika aku masih muda dan lemah, ayahku memberi nasihat yang selalu melekat dalam benakku hingga sekarang.
"Kapan pun kau merasa ingin mencela orang lain," katanya, "ingatlah bahwa tidak semua orang di dunia ini memiliki kelebihan seperti yang kaumiliki."
Ia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi kami memang jarang berkomunikasi secara terbuka, dan aku mengerti bahwa yang ia maksudkan lebih banyak dari yang ia sampaikan. Sebagai gantinya, aku menjadi seseorang yang cenderung memendam penghakiman-penghakimanku, sebuah kebiasaan yang kemudian menumbuhkan rasa penasaran dalam diriku dan menjadikanku korban dari orang-orang yang sangat membosankan. Pikiran abnormal cepat menemukan dan melekatkan dirinya pada sifat seperti ini saat ia muncul dalam diri seseorang yang normal. Saat kuliah aku pernah dituduh sebagai seseorang yang manipulatif secara semena-mena, karena aku mengetahui duka terpendam orang-orang yang asing dan liar. Kebanyakan rahasia itu kudapatkan secara tak disengaja—sering kali aku sedang bepura-pura tidur, asyik sendiri, atau berkelakar ketika aku menyadari pertanda tak terelakkan bahwa akan ada rahasia pribadi yang segera terungkap. Sebab rahasia pribadi para lelaki belia, atau setidaknya istilah-istilah yang mereka gunakan untuk mengungkapkannya, biasanya hanya tiruan dari yang lain dan jelas-jelas dilukai oleh rasa tertekan untuk memendamnya.
Memendam penghakiman adalah harapan yang tak terbatas. Aku masih agak khawatir akan melewatkan sesuatu jika melupakan bahwa, seperti yang pernah disampaikan ayahku dengan angkuhnya, dan aku ulangi pula dengan sama angkuhnya, kesadaran akan sopan santun dibagikan secara tak merata ketika manusia lahir.
Setelah membual begini soal toleransiku, harus kuakui bahwa toleransi memiliki batas. Perilaku mungkin saja dibentuk di atas batu keras atau rawa-rawa yang basah, tetapi pada titik tertentu aku tidak peduli lagi di mana perilaku dibentuk. Ketika aku kembali dari Timur musim gugur lalu, aku merasa bahwa aku menginginkan dunia menjadi seragam dan memperhatikan moral selamanya; aku tidak mau lagi ada perjalanan-perjalanan rusuh dengan cuplikan-cuplikan isi hati manusia yang ikut terlihat.
Hanya Gatsby, lelaki yang namanya menjadi judul buku ini, yang tidak terpengaruh oleh reaksiku. Gatsby, yang mewakili segala hal yang paling tak kuhormati. Jika kepribadian adalah rangkaian kokoh keberhasilan, maka ada sesuatu yang indah dalam dirinya, semacam kepekaan akan janji-janji kehidupan, seolah-olah ia terhubung dengan mesin canggih yang dapat merekam gempa sepuluh ribu mil jauhnya. Daya tanggap ini tidak ada hubungannya dengan sikap mudah terkesannya yang lembek tetapi disanjung sebagai "temperamen kreatif"—itu adalah bakat luar biasa untuk harapan, sebuah kesiapan romantis yang tidak pernah kutemui dalam diri orang lain dan mungkin tidak akan pernah kutemui lagi. Tidak—Gatsby lumayan saja pada akhirnya. Hal yang memangsa Gatsbylah, debu busuk yang melayang membuyarkan mimpi-mimpinya, yang untuk sementara menutupi ketertarikanku akan kesedihan-kesedihan penuh kegagalan dan kegembiraan singkat manusia.
---
Keluargaku sudah menjadi orang-orang terpandang di Middle Eastern City ini selama tiga generasi. Keluarga Carraway merupakan semacam klan, dan kami memiliki kepercayaan turun-temurun yang meyakini bahwa kami adalah keturunan Dukes of Buccleuch, meski leluhur asli garis keturunanku adalah saudara lelaki kakekku, yang datang kemari pada tahun lima puluh satu, mengirim seorang pengganti ke Perang Sipil, dan memulai bisnis grosir perkakas yang dilanjutkan ayahku hingga hari ini.
Aku tidak pernah bertemu dengan saudara kakekku itu, tetapi kurasa aku mirip dengannya—cukup dengan referensi lukisan berwajah keras yang tergantung di kantor Ayah. Aku lulus dari New Haven pada tahun 1915, tepat seperempat abad setelah ayahku, dan tidak lama kemudian aku bergabung dengan migrasi Teutonik yang sempat tertunda, yang dikenal sebagai Perang Akbar. Aku begitu menikmati serangan balik itu sehingga saat kembali aku merasa gelisah. Alih-alih menjadi pusat dunia yang hangat, Middle West sekarang tampak seperti tepian semesta yang berantakan—jadi kuputuskan untuk pergi ke Timur dan mempelajari bisnis obligasi. Semua orang yang kukenal melakukan bisnis obligasi, sehingga kukira bisnis itu bisa menyokong satu lagi lelaki lajang. Semua bibi dan pamanku merundingkannya seolah-olah mereka tengah memilih sekolah persiapan untukku, dan akhirnya berkata, "Ya—baiklah," dengan ekspresi muram penuh keraguan. Ayah setuju untuk membiayaiku selama setahun, dan setelah berbagai penundaan aku sampai di Timur, secara permanen, kurasa, di musim semi tahun dua puluh dua.
Hal yang praktis untuk dilakukan adalah mencari kamar sewa di kota, tetapi waktu itu sedang musim yang hangat, dan aku baru saja meninggalkan pedesaan dengan halaman-halaman yang luas dan pepohonan yang rindang. Jadi ketika seorang pemuda di kantor mengajakku menyewa rumah bersama agak jauh dari kota, ide itu terdengar sangat bagus. Ialah yang menemukan rumah itu, sebuah bungalo yang dinding papannya lapuk termakan cuaca dengan harga sewa delapan puluh dolar sebulan. Walau begitu, tiba-tiba saja perusahaan memindahkannya ke Washington, jadi aku pergi ke daerah pedesaan itu seorang diri. Aku punya seekor anjing—paling tidak aku memeliharanya selama beberapa hari sampai dia melarikan diri—dan sebuah mobil Dodge tua, serta seorang perempuan Finlandia yang merapikan kamarku dan memasak sarapan, dan senang menuturkan wejangan-wejangan dalam bahasa Finlandia pada dirinya sendiri di dekat kompor listrik.
Selama beberapa hari aku merasa kesepian, sampai suatu pagi seorang pria yang tiba lebih belakangan daripada aku, mencegatku di jalan.
"Bagaimana caranya pergi ke desa West Egg?" ia bertanya dengan putus asa.
Aku memberitahunya. Dan ketika aku kembali melangkah, aku tak lagi merasa kesepian. Aku adalah pemandu, penunjuk jalan, pemukim asli. Tanpa disadarinya, pria itu telah menganugerahiku kebebasan di lingkungan itu.
Maka, dengan cerahnya cuaca dan tumbuhnya hamparan dedaunan di pohon-pohon, sebagaimana banyak hal bertumbuh dengan cepat di film-film, aku merasakan perasaan yakin yang familier bahwa kehidupan akan dimulai kembali dengan hadirnya musim panas.
Di satu sisi, ada begitu banyak yang harus dibaca, dan begitu banyak kesegaran menyehatkan yang bisa kuserap dari udara. Aku membeli selusin buku tentang perbankan dan kredit dan saham investasi. Buku-buku itu berdiri di rak bukuku dengan warna merah dan emas seperti uang baru dari percetakan, menjanjikan terungkapnya rahasia-rahasia berkilau yang hanya Midas dan Morgan dan Maecenas yang tahu. Dan aku bertekad untuk membaca lebih banyak buku lagi. Aku cukup cakap di bidang sastra semasa kuliah—aku pernah menulis sebuah serial editorial yang serius dan mudah dipahami untuk Yale News selama setahun—dan sekarang aku akan membawa segala hal itu kembali ke dalam hidupku, dan kembali menjadi yang tercakap di antara yang cakap, "lelaki yang serbabisa." Ini bukanlah epigram belaka—toh kehidupan dianggap lebih berhasil jika dilihat dari satu jendela saja.
Suatu kebetulanlah yang membawaku untuk menyewa rumah di salah satu area paling aneh di Amerika Utara. Tempat itu berada di pulau ramai yang membentang di sebelah timur New York—dan tempat terdapat, di antara keanehan-keanehan alam lainnya, dua formasi daratan yang tidak biasa. Dua puluh mil dari kota, bagai sepasang telur raksasa dengan kontur identik dan hanya dipisahkan oleh teluk kecil, yang menjorok ke perairan asin yang paling tenang di belahan bumi bagian Barat, lahan pertanian basah nan luas di Long Island Sound. Bentuknya tidak oval sempurna—seperti telur dalam kisah Columbus, keduanya dibenturkan hingga rata di area persinggungannya—tetapi kemiripan bentuk mereka pastilah menjadi sumber kekaguman bagi burung camar yang terbang mengelilinginya. Bagi yang tidak bersayap, fenomena yang lebih menarik adalah ketidaksamaan mereka dalam segala hal kecuali bentuk dan ukurannya.
Aku tinggal di West Egg, yang—ya, yang paling tidak bergaya dari keduanya, walaupun itu sebutan yang sangat dangkal untuk mengungkapkan perbedaan aneh dan mengerikan di antara mereka. Rumahku berada tepat di ujung telur itu, hanya empat puluh lima meter lebih sedikit dari Sound, dan diapit dua bangunan yang disewa seharga dua belas sampai lima belas ribu dolar semusim. Di sebelah kanannya berdiri bangunan yang dari segi mana pun terlihat kolosal—tiruan persis Hôtel de Ville di Normandy, dengan satu menara di satu sisi, bangunan baru berlapis tanaman rambat liar yang tipis, sebuah kolam renang dari marmer, dan taman serta pekarangan seluas lebih dari empat puluh ekar. Itulah wastu milik Gatsby. Sebetulnya, karena aku tidak mengenal Mr. Gatsby, wastu itu adalah kediaman seorang pria yang bernama Gatsby. Rumahku sendiri hanya rumah reyot, kecil sekali, sehingga mudah diabaikan. Jadi aku memiliki pemandangan ke arah lautan, sebagian pekarangan tetangga, dan menjadi tetangga para miliuner—semua ini hanya untuk delapan puluh dolar sebulan.
Di seberang teluk kecil itu terdapat istana-istana putih East Egg yang megah berpendar bersama permukaan air, dan sejarah dalam musim panas ini dimulai pada malam aku berkendara ke sana untuk makan malam bersama Tom Buchanan. Daisy adalah sepupu jauhku, dan aku mengenal Tom saat kuliah. Dan tepat setelah perang aku menghabiskan dua hari bersama mereka di Chicago.
Suami Daisy, di antara pencapaian-pencapaian fisik lainnya, pernah menjadi salah satu atlet terhebat yang bermain football di New Haven—bisa dibilang dia seorang tokoh nasional, salah seorang lelaki yang bisa mencapai kejayaan yang belum tentu dimiliki orang lain di usia dua puluh satu, yang membuat segalanya yang terjadi setelah masa-masa itu terasa seperti antiklimaks. Keluarganya luar biasa kaya—bahkan di kampus dulu, kebebasan finansialnya menjadi bahan pergunjingan. Tetapi sekarang, dia telah meninggalkan Chicago dan tinggal di East dalam gaya hidup yang dapat membuatmu terperangah: misalnya, ia membeli sekelompok kuda poni untuk bermain polo dari Lake Forest. Sungguh sulit membayangkan seorang lelaki yang segenerasi denganku cukup kaya untuk melakukannya.
Mengapa mereka tinggal di East, aku tidak tahu. Mereka pernah tinggal setahun di Prancis tanpa alasan yang jelas, kemudian berpindah-pindah ke sana kemari di mana pun orang-orang yang kaya dan senang bermain polo seperti mereka berada. Kali ini mereka akan menetap, Daisy pernah berkata lewat telepon, tetapi aku tidak memercayainya. Aku tidak dapat melihat ke dalam hati Daisy, tetapi aku merasa bahwa Tom akan terus selamanya berkelana untuk mencari, dengan agak sedih, gelora dramatis permainan-permainan football yang tak bisa diulang kembali.
Begitulah yang terjadi di suatu malam yang hangat dan berangin ketika aku berkendara ke East Egg untuk menemui dua teman lama yang sebenarnya tidak benar-benar kukenal. Rumah mereka bahkan lebih megah dari yang kubayangkan, sebuah wastu bergaya kolonial Georgia bercat merah dan putih ceria yang menghadap ke arah teluk. Pekarangannya bermula dari pantai dan terus membentang sampai ke pintu utama sepanjang seperempat mil, melewati beberapa jam matahari dan jalan setapak dari batu bata dan taman-taman penuh warna—dan ketika mencapai rumah, menyimpang ke sisinya bagai sulur-sulur terang yang seakan-akan meraih puncak momentumnya. Bagian depan rumah dihiasi sebaris jendela bergaya Prancis, yang sekarang tampak berkilau keemasan dan terbuka lebar menyambut hangatnya semilir udara sore. Tom Buchanan dalam pakaian berkudanya, berdiri dengan kaki terbuka lebar di beranda depan.
Ia telah berubah sejak masa-masa New Haven-nya. Sekarang, ia adalah lelaki tiga puluhan berbadan tegap dengan rambut serupa jerami, dengan mulut tajam dan pembawaan angkuh. Pendar arogan dalam kedua matanya tampak mendominasi wajahnya dan memberinya kesan seakan-akan ia selalu berdiri terlalu condong ke depan. Bahkan kegemulaian seragam berkudanya tidak bisa menyembunyikan keperkasaan tubuhnya—kedua kakinya seakan-akan memenuhi sepatu bot berkilaunya hingga tali-talinya tertarik kencang, dan kau dapat melihat otot-ototnya menggeliat ketika bahunya bergerak di balik mantel tipisnya. Itu tubuh dengan kekuatan yang dahsyat—tubuh yang kejam.
Suaranya saat berbicara, tenor yang rendah dan parau, menambah kesan sangar yang ia tampilkan. Ada sentuhan angkuh dalam suaranya itu, bahkan terhadap orang-orang yang ia sukai—dan ada beberapa orang di New Haven yang memang membenci keberaniannya.
"Nah, jangan kau kira pendapatku tentang persoalan ini sudah final," ia seakan-akan berkata, "hanya karena aku lebih kuat dan lebih jantan daripada kau." Kami berada dalam lingkungan senior yang sama, dan walaupun kami tidak pernah dekat, aku selalu memiliki kesan bahwa ia menerimaku dan ingin aku menyukainya dengan caranya sendiri, yang kasar dan menantang.
Kami berbincang sebentar di beranda yang disirami cahaya matahari.
"Aku memiliki tempat tinggal yang bagus di sini," katanya, matanya berkeliling ke segala arah.
Dengan satu tangannya ia menarikku untuk mengikuti arah pandangnya, sambil menunjuk pemandangan di depan dengan tangan satunya, taman bergaya Italia yang memiliki cekungan membentang luas, setengah ekar mawar yang sangat harum, dan kapal motor bermoncong pendek yang diombang-ambing gelombang air laut.
"Itu punya Demaine, si tukang minyak." Ia menarikku lagi, dengan sopan dan tiba-tiba. "Kita masuk."
Kami berjalan melewati koridor berlangit-langit tinggi ke dalam ruangan berwarna serupa mawar yang terang, yang tampak rikuh tersambung pada bangunan utama dengan jendela-jendela bergaya Prancis di kedua ujungnya. Jendela-jendela itu terbuka lebar dan berkilau putih dilatari rumput segar di luar yang tampaknya tumbuh sedikit melewati batas rumah. Hawa semilir memasuki ruangan, mengembus tirai hingga berkibar-kibar seperti bendera pucat, memuntirnya ke arah langit-langit sewarna kue pengantin, dan mengayunkannya di atas karpet berwarna merah anggur, menciptakan bayang-bayang di atasnya seperti yang dilakukan angin pada air laut.
Satu-satunya benda yang diam dalam ruangan itu adalah sofa besar yang tengah ditempati dua perempuan muda, yang duduk terayun-ayun seperti sedang menaiki balon udara yang tengah berlabuh. Mereka mengenakan pakaian berwarna putih, dan gaun mereka berombak berkibar-kibar seolah mereka baru saja tertiup masuk setelah terbang mengelilingi rumah. Tampaknya aku hanya berdiri termangu selama beberapa saat mendengarkan lecutan dan sentakan tirai-tirai dan erangan lukisan di dinding. Lalu terdengar bunyi berdebum ketika Tom Buchanan menutup daun jendela dan menghalau angin yang hendak masuk ke ruangan. Tirai-tirai, karpet, dan kedua perempuan muda itu pun bagaikan mendarat dengan pelan ke lantai.
Perempuan yang terlihat lebih muda dari yang satunya tampak asing bagiku. Ia berbaring di dipan sofa, tak bergerak sedikit pun dengan dagu agak terangkat, seolah ia hendak menyeimbangkan sesuatu yang akan jatuh dari sana. Jika ia memandangku melalui sudut matanya, ia tak menunjukkan gelagat itu sama sekali—justru, akulah yang hampir terkejut hingga meminta maaf telah mengganggunya dengan masuk ke ruangan itu.
Perempuan yang satunya, Daisy, berusaha untuk bangkit—ia mencondongkan tubuhnya ke depan dengan ekspresi bersungguh-sungguh—kemudian tertawa, tawa kecil yang secara aneh memesonakan, dan aku pun ikut tertawa seraya memasuki ruangan.
"Aku lu-lumpuh karena terlalu bahagia."
Ia tertawa lagi, seolah telah mengatakan sesuatu yang begitu lucu, dan menggenggam tanganku sebentar, menatap wajahku, dengan raut seakan-akan tidak ada orang lain di dunia yang lebih ingin ia temui. Begitulah ia. Ia memberitahuku dengan bergumam bahwa nama belakang gadis yang berbaring itu Baker. (Kudengar Daisy bergumam hanya agar orang-orang mencondongkan tubuh kepadanya; itu pendapat tak penting yang tidak mengurangi pesonanya sama sekali.)
Entah bagaimana, bibir Miss Baker bergetar. Ia mengangguk kepadaku hampir tak kentara, kemudian dengan cepat merebahkan kepalanya kembali—benda yang diseimbangkannya jelas sedikit goyah dan sedikit menakutinya. Lagi-lagi, permintaan maaf terlontar dari mulutku. Hampir segala sikap yang ditampilkan dengan penuh rasa percaya diri selalu saja membuatku terpana.
Aku memandang sepupuku lagi, yang mulai menanyaiku dengan suaranya yang rendah dan menggetarkan. Suaranya itu jenis yang akan dicermati oleh telinga siapa pun, seolah-olah setiap ujarannya disusun sesuai notasi yang tidak akan pernah dimainkan lagi. Wajahnya muram dan ayu dengan fitur-fitur yang tampak berkilau, seperti mata cemerlang dan bibir berseri yang menggairahkan. Tetapi, ada antusiasme dalam suaranya yang membuat para lelaki yang memujanya sulit untuk lupa: dorongan untuk bernyanyi, bisikan kata "Dengar", perasaan menjanjikan bahwa ia telah melakukan hal-hal menarik dan menyenangkan beberapa saat tadi, dan masih akan ada hal-hal menarik dan menyenangkan nantinya.
Aku memberitahunya bahwa aku sempat singgah di Chicago selama sehari dalam perjalananku ke East, dan selusin orang menitipkan salam sayang untuknya melalui aku.
"Mereka merindukanku?" ia memekik dengan gembira.
"Seluruh kota merana. Ban depan sebelah kiri semua mobil dicat warna hitam bagaikan serangkaian bunga duka, dan ratapan terus terdengar di malam hari di sepanjang pesisir utara."
"Betapa indahnya! Ayo kita kembali, Tom. Besok!" Lalu ia menambahkan dengan tidak nyambung, "Kau harus lihat bayinya."
"Boleh saja."
"Ia sedang tidur. Usianya tiga tahun. Belum pernahkah kau melihatnya?"
"Belum pernah."
"Nah, kau harus melihatnya. Ia—"
Tom Buchanan, yang sejak tadi mondar-mandir tak tenang di sekitar ruangan, berhenti dan meletakkan tangannya di bahuku.
"Apa yang kaukerjakan, Nick?"
"Aku bekerja di bisnis obligasi."
"Dengan siapa?"
Aku memberitahunya.
"Tidak pernah kudengar sebelumnya," katanya tanpa keraguan.
Ini membuatku sebal.
"Kau akan mengenal mereka," kataku cepat, "jika kau menetap di East."
"Oh, tentu aku akan menetap di East, jangan khawatir," katanya, memandang Daisy lalu beralih kembali kepadaku, seolah-olah ia bersiaga akan sesuatu. "Aku pasti sangat bodoh jika tinggal di tempat lain."
Mendengar hal ini Miss Baker berkata, "Tentu saja!" dengan begitu tiba-tiba hingga aku terkejut. Itu kata-kata pertama yang diucapkannya sejak kehadiranku di ruangan ini. Ternyata ia pun terkejut sama sepertiku, sebab kemudian ia menguap dan dengan gerakan tergesa-gesa bangkit berdiri.
"Tubuhku terasa kaku," ia mengeluh, "Aku berbaring di sofa itu lama sekali."
"Jangan menatapku," Daisy membalasnya. "Aku berusaha mengajakmu ke New York sepanjang sore ini."
"Tidak, terima kasih," ucap Miss Baker menolak empat gelas koktail yang baru saja diantarkan masuk dari pantri. "Aku sedang dalam masa pelatihan."
Sang tuan rumah memandangnya tidak percaya.
"Tentu saja!" Tom menenggak minumannya seolah-olah isinya hanya setetes. "Sulit kupercaya bagaimana kau mampu menyelesaikan segalanya."
Aku memandang Miss Baker, penasaran hal apa yang ia "selesaikan." Menyenangkan sekali memandangnya. Ia adalah gadis ramping, berdada kecil, dengan postur tegak, yang dipertegas gestur bahunya yang condong ke belakang selayaknya seorang kadet muda. Mata abu-abunya yang tertimpa cahaya matahari balas memandangku dengan pancaran sorot ingin tahu seraut wajah pucat dan menawan yang merona sedih. Kusadari aku pernah melihatnya, atau potret dirinya, di suatu tempat sebelumnya.
"Kau tinggal di West Egg," katanya meremehkan. "Aku punya kenalan di sana."
"Aku tidak mengenal siapa—"
"Kau pasti kenal Gatsby."
"Gatsby?" desak Daisy. "Gatsby siapa?"
Sebelum aku dapat menyahuti bahwa pria itu adalah tetanggaku, makan malam telah diumumkan. Sambil menggamitku dengan lengannya yang tegang, Tom Buchanan menggiringku ke luar ruangan itu seperti menggerakkan bidak catur ke kotak lain.