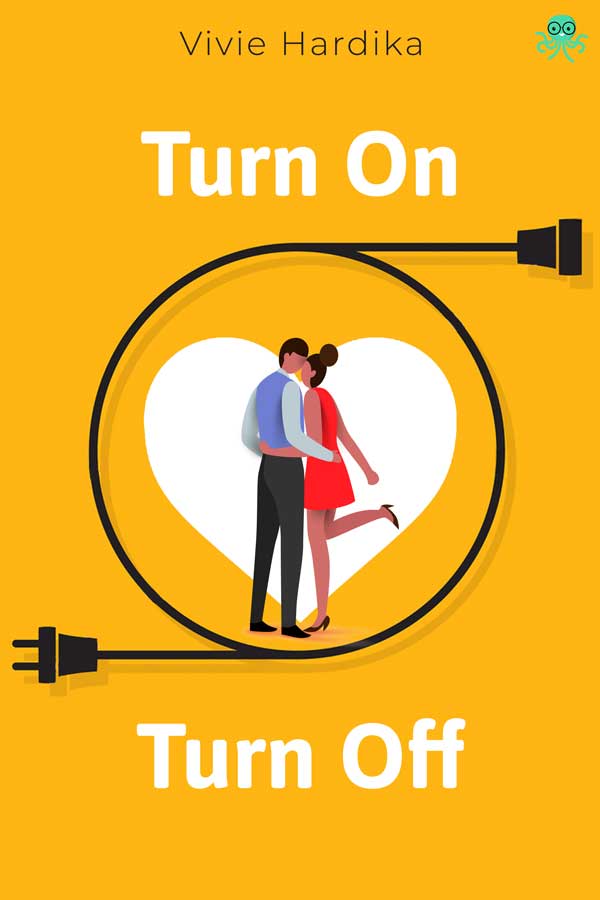
Turn On Turn Off
By Vivie Hardika
“Anna mau pulang,” seorang gadis kecil merengek begitu kedua matanya terbuka. Tangis pilu di wajahnya membuat siapa pun yang melihatnya menjadi nelangsa. “Mama….”
Tangis gadis kecil berusia 4 tahun itu semakin menjadi-jadi kala sosok yang paling dibutuhkannya belum juga memeluknya. Seluruh wajahnya memerah dan basah.
Rakha, pria yang sedari tadi berusaha membuat Anna tenang semakin kelimpungan. Ia tidak mahir membuat anak kecil berhenti menangis.
“Anna, Sayang… Mama ada kok, sebentar ya, Sayang,” suara berat itu berusaha untuk menenangkan.
Anna masih menangis dan tak mengindahkan bujukan Rakha sama sekali. Anna terus menangis memanggil mama dan papanya bergantian.
Rakha meremas rambutnya, berharap sebuah ide muncul tetapi sayang ide yang diharapkannya tak kunjung memenuhi kepalanya. Ia bahkan sempat mengambil ponselnya, menelepon Nafa—mama Anna—berulang kali. Namun, tak ada jawaban.
Sebelum akhirnya menemukan Anna di salah satu kamar rawat anak, ia tidak tahu mengapa suara Nafa begitu terburu-buru menyuruhnya datang. Kebingungannya semakin bertambah ketika melihat Anna sendirian di kamar rawat, sementara Nafa tak ditemukan di setiap sudut ruangan.
“Shit!”
Rakha tak sadar mengumpat karena tak bisa menghubungi Nafa berkali-kali. Harus bagaimana ia menghadapi tangisan Anna?
“Anna… Di sini dulu sama Om Rakha, ya,” Rakha mengedarkan pandangannya ke sekeliling, berusaha mencari sesuatu yang sekiranya dapat menenangkan Anna. Sekelebat, sesuatu yang ia butuhkan terlintas di kepalanya setelah melihat gambar di baju Anna.
“Ah!” suaranya setengah berteriak. “Nanti kita beli boneka kuda poni, ya.”
Suara tangisnya sedikit teredam begitu mendengar nama tokoh kartun favoritnya.
“Anna suka kuda poni, kan?”
Meski masih merengek, Anna mengangguk dan berangsur-angsur tangisannya memudar, terbujuk oleh iming-iming Rakha yang selalu menepati janji membelikan mainan yang disukainya. Anna bahkan masih ingat ada berapa boneka yang sudah diberikan Om Rakha padanya.
“Tapi ini sakit. Anna nggak mau di sini, Om. Anna mau mama… Anna takut di sini…”
Rakha mengecup pipi Anna kilat dan berkata, “Masa sih? Sini yang sakit om kecup, biar nggak sakit lagi.”
Dengan sukarela Anna menyodorkan lengan kanannya seraya berucap, “Anna kemarin jatuh dari ayunan. Sakit sekali. Sampai demam begini.”
Seraya ia mengusap pelan rambut gadis kecil itu, Rakha terus mendengarkan celotehan Anna yang terdengar seperti mengadu. Anna memang sangat dekat dengan Rakha, Om yang dikenal Anna sebagai Om yang suka memberinya hadiah boneka dan membelikannya es krim tanpa sepengetahuan Nafa. Setiap minggu Anna akan merengek minta bertemu dengan Rakha dan tak jarang Rakha lah yang menjemput anak sahabatnya itu di rumah.
Kemarin siang, Nafa meneleponnya dengan suara yang parau. Rakha mulai curiga sesuatu yang buruk terjadi pada Nafa sampai akhirnya kecurigaannya terbukti dengan sebuah pesan panjang Nafa yang mengatakan bahwa Evand, suaminya mengetahui sebuah rahasia yang sudah terkubur lama.
Rakha menatap nanar gadis kecil polos yang tengah tertidur dengan damainya di pangkuannya.
Maafkan saya….
***
Jari-jari yang tadinya aktif menekan huruf demi huruf di atas keyboard, tiba-tiba saja berhenti bersamaan dengan desahan napas kesal. Isi kepalanya nyaris saja meledak ketika membaca judul berita yang diterimanya melalui E-mail.
Gadis bernama Samara itu meregangkan otot leher dan jari-jarinya hingga berbunyi kretek. Sejurus kemudian, helaan napasnya kembali berat.
“Harus kuapakan berita kayak begini?”
Kekesalannya belum juga berakhir. Samara memukul meja dengan kepalan tangannya dan membuat semua orang yang ada di ruangan itu melihat ke arahnya dengan wajah bingung. Namun tak berlangsung lama, sebab hanya berselang beberapa detik saja semuanya kembali membuang muka seraya tersenyum kecil.
Hanya laki-laki yang duduk di sebelah Samara yang mendekat dan menyodorkan kipas portable ke arahnya.
Samara menengok ke arah laki-laki bernama Samuel itu dengan tatapannya yang tajam bak singa yang siap menyantap mangsanya. Memang tak tepat sasaran, tetapi Samuel tak pernah jera untuk menggoda Samara di kala emosinya nyaris ke ubun-ubun.
Pria keturunan Chinese tersebut malah menyeringai. Dengan kipas portable yang masih mengarah pada Samara, kedua matanya yang sipit melirik layar komputer Samara dan tertawa geli.
“Udahlah, lu pensiun aja jadi editor entertainment artis sensasi gitu, terus gabung ke divisi gue,” katanya enteng.
“Nggak usah ngaco deh, Wel. Istilah per-IT-an lu itu lebih njlimet,” ketus Samara.
Samuel tertawa keras melihat reaksi Samara barusan. Baginya, tak ada yang lebih lucu dari muka kesal Samara di dunia ini.
Samara memang mencintai pekerjaannya sebagai penulis dan editor di portal berita berbasis online Zonaharian.com, terlebih divisi entertainment yang dipercaya bisa membawanya ke impian terbesarnya untuk menjadi salah satu penulis naskah film. Tetapi, fakta di lapangan di mana dunia jurnalis lebih mementingkan sensasi daripada prestasi membuat Samara kesal.
Sepanjang karirnya sebagai reporter ia bersumpah untuk tidak menulis tentang artis yang hanya mengumbar sensasi atau gimmick semata, tetapi kini ia terjebak.
“Kalau tau entertainment negara ini makin ke sini makin menjijikkan, gue nggak akan merintis karier gue ini dari jaman ospek kuliah,”
Tawa Samuel semakin menyembur. Pernyataan itu sudah seribu kali didengarnya, tetapi semakin lama terdengar sangat lucu.
“Well, lu mau jadi kaum rebahan doang, gitu?”
Samara refleks memukul kepala Samuel yang tak juga berhenti meledeknya. “Coba lu baca berita ini. Bebi Permata Sari Ketahuan Jalan Bareng Pria Negeri Jiran, Sudah Cerai dari Suami? Coba lu telaah baik-baik, apa faedahnya rumor perselingkuhan Bebi Permata Sari dengan pertumbuhan ekonomi negara ini?”
Bagi Samuel, Samara adalah rekan kerja yang lebay dan drama.
“Lebay lu!” Samuel menoyor kepala Samara hingga poninya berantakan. “People jaman now itu cuma butuh bahan buat julid, dan berita ini cocok buat nitizen mengeluarkan jiwa ghibahnya!”
“Nggak bisa. Ini bertentangan dengan naluri gue, lu tau, kan?”
“Tapi kan nitizen julid nggak tau ini sesuai naluri lu apa enggak, dodol!”
Samara semakin frustrasi. Bicara dengan Samuel memang selalu membuatnya semakin kesal. Diacak-acaknya rambut sebahunya hingga berantakan dan menutupi wajah.
Hari ini saja, ia telah menerima 20 puluh tulisan dari reporter tentang artis yang sama dan kesemuanya bertema sama. Rasanya sudah sangat muak memperingatkan mereka untuk tidak menulis berita bernada sama, tetapi tidak pernah berhasil. Bahkan di setiap evaluasi bulanan, selalu mendapat peringatan karena melewatkan berita semacam itu dari pimred. Jika ia tetap menerapkan sikap idealisnya, nominal sallary-nya pun tak segan-segan dipotong.
Samara Alfara telah menekuni dunia tulis-menulis sejak duduk di bangku SMP. Sebuah kisah membawanya sampai ke titik ini, di mana tidak semua penulis seusianya dapat meraih hal tersebut.
Gadis itu memulai karier menulisnya di usia 17 tahun sebagai penulis freelance di Zonaharian.com, ketika ia baru lulus SMA. Meski berhonor kecil, baginya cukup untuk menambah uang jajan dan menambah pengalamannya di dunia kepenulisan. Maklum, Samara awalnya hanya menulis cerita pendek roman picisan di media cetak. Waktu itu media cetak masih menguasai pasar dan Samara salah satu penulis yang rajin mengisi rubrik cerpen.
Karena Ia mengambil jurusan komunikasi, Samara pun memilih magang di Zona Harian sebagai reporter dan setelah kelulusan barulah ia resmi menjadi salah satu karyawannya. Perjalanan karier Samara di Zonaharian.com terbilang mulus karena hanya dalam 2 tahun saja ia dipromosikan sebagai seorang editor.
Menjadi seorang editor di media online memang tidak mudah, karena bisa saja ia tidak punya waktu untuk istirahat atau sekadar rebahan di kasur kesayangannya. Tetapi ia cukup menikmatinya, terlebih ketika ia harus pergi mewawancarai artis kelas A Indonesia secara ekslusif atau diundang ke premier film-film bergengsi. Semua itu dapat dijadikan cambukan agar tidak mudah mengeluh.
Meski terkadang ia harus menahan sumpah sarapahnya ketika harus berhadapan dengan artis-artis doyan sensasi dan menjual gimmick belaka.
Selamat datang di dunia yang memaksamu untuk realistis.
***
Tidak sulit menemukan alamat rumah Rashid Hariwibawa yang berada di bilangan Menteng. Rakha sudah langsung menemukan rumah omnya hanya beberapa meter dari pos penjagaan. Terakhir kali ia ke rumah itu 10 tahun lalu, tetapi tetap tak banyak yang berubah kecuali bentuk pagarnya yang semakin tinggi.
Sekarang ia kembali lagi ke rumah itu karena permintaan Rashid untuk membantunya di media yang dibangunnya sejak 5 tahun lalu. Dua hari sebelum keberangkatannya ke Jakarta, Rakha mendapat telepon dari Nafa yang memintanya untuk menjaga Anna dalam beberapa waktu. Rakha tidak punya alasan untuk menolak permintaan Nafa di tengah krisis yang melanda rumah tangganya.
Rakha sempat berpikir untuk menitipkan Anna kepada kedua orangtuanya dan pergi ke Jakarta sendiri, tetapi hal itu akhirnya tak dapat dilakukannya mengingat kesibukan orangtuanya mengurus restoran keluarga yang padat.
Setelah berpikir panjang, Rakha mantap membawa Anna bersamanya ke Jakarta.
Bagi Rakha, Anna sama berartinya dengan Nafa, sahabat yang telah menemaninya sejak masa kanak-kanak. Kedua wanita ini bagian yang sangat penting dalam hidupnya, dan ia bertaruh tak akan bisa menjalani hari-harinya jika salah satu dari mereka pergi dari hidupnya.
Dibantu sopir taksi Rakha menurunkan barang-barangnya, kemudian menggendong Anna yang masih tertidur sejak perjalanan panjang dari Bali tadi pagi. Gadis kecil itu kini terbangun, membuat Rakha sedikit merasa bersalah.
“Oh maaf, maaf. Om ganggu tidur Anna, ya?” tanyanya seraya mengecup pipi Anna.
Ajaib, Anna tidak menangis barang sebentar pun. Gadis kecil itu melihat ke sekelilingnya dengan berjuta tanda tanya di kepalanya.
“Om, ini kan bukan rumahku,” Anna terlihat memberenggut. Ia berpikir ia akan pulang ke rumahnya dan menemui ibu yang sudah sangat dirindukannya.
“Ini rumah Om Rakha,” jawabnya.
“Kok rumah Om Rakha banyak banget?”
Rakha mencubit hidung bangir Anna dan mengatakan, “Di rumah ini ada piano seperti di rumah Anna, lho. Anna pasti suka. Siapa yang waktu itu bilang pengin jago main piano seperti mama?”
Anna menepuk dadanya. Raut wajahnya benar-benar polos.
“Nah, Anna nanti les pianonya di sini sama Om Rakha. Kan mau bikin surprise buat ulang tahun Mama,” iming Rakha.
“Ah, iya. Aku lupa,” sejurus kemudian Anna mengecup pipi Rakha sembari mengucapkan terima kasih karena telah merahasiakan keinginannya untuk bermain piano dari sang mama. “Om Rakha baiiikkk sekali!”
Setelah memasuki pekarangan, Anna meminta Rakha menurunkannya begitu melihat kandang kelinci di bagian samping rumah. Rakha tidak bisa menemani Anna yang langkah kakinya sangat cepat dan memilih untuk membawa masuk barang-barangnya. Sembari mengangsur kopernya, Rakha melihat Anna yang larut memberi makan kelinci yang ditebaknya adalah peliharaan Alfian, putra bungsu Rashid yang baru berusia 11 tahun.
Dari dalam rumah, samar-samar terdengar suara Maya yang berjalan keluar untuk menyambutnya. Ia juga meminta bantuan untuk membantu Rakha.
“Tante, apa kabar?” Rakha langsung bersalaman dengan istri Rashid tersebut dan memeluknya.
“Kamu kenapa nggak calling tante, sih? Kan tante bisa jemput,” omel Maya.
Rakha tersenyum kecil, tantenya ini juga masih sama. Masih suka mengomel jika tidak dilibatkan atau direpotkan dalam urusan remeh seperti ini.
“Rakha kan udah bukan anak kecil yang perlu dijemput lagi, Tan.” Rakha berseloroh.
“Om masih di kantor. Sudah telepon kalau sudah sampai?”
Rakha menggeleng dan memberi jawaban akan meneleponnya nanti. Orang sesibuk Rashid mana mungkin sempat menjawab telepon di siang bolong begini. Maka ia memilih untuk membiarkan omnya tahu ketika sampai di rumah saja. Lagi pula, sedari awal omnya itu juga tahu kapan Rakha akan ke Jakarta.
“Ya udah langsung masuk. Kamar kamu masih sama, kok.” Maya menepuk lengan Rakha sebagai isyarat bahwa tantenya siap menggiring Rakha ke kamarnya.
“Sebentar, Tan,” Rakha meliarkan pandangan, mencari Anna yang sudah tak terlihat di depan kandang kelinci.
Maya refleks mengikuti arah pandang Rakha dan tampak terkejut begitu melihat Anna muncul dari samping rumah dan berlari-lari kecil ke arah mereka dengan kelinci peliharaan Alfian.
“Anna, sini, kenalan sama Oma Maya!”
Maya yang mendengarnya seperti mendapat sengatan listrik. Ia sama sekali tidak tahu menahu mengenai gadis kecil yang sekarang sudah berada dalam gendongan Rakha dengan sangat nyaman.
“Lho, kamu kapan nikahnya, kok tau-tau udah punya anak?”
Mati aku!
Maya memang tidak tahu siapa Anna, karena ia juga tidak begitu mengenal Nafa. Sejak melahirkan Alfian, Maya tidak pernah lagi ikut berkunjung ke Bali bersama omnya Alasannya tak kuat mengikuti jadwal Rashid yang super sibuk. Tentu saja, omnya yang seorang pimpinan media online itu bepergian ke Bali hanya untuk urusan bisnis dan sekali-kali mampir sebentar ke restauran orangtua Rakha jika punya waktu luang.
Maya memang pernah bertemu Nafa sekali, dan itu ketika Rakha dan Nafa masih menjadi murid SMA. Sudah lama sekali, wajar jika Maya lupa bahkan tidak tahu jika ada temannya yang bernama Nafa.
“I-ini anaknya Nafa, Tan,” Rakha kemudian berbicara pada Anna dan menyuruhnya memberi salam yang kemudian disambut Maya dengan segurat senyum yang ramah.
Rakha tidak berharap banyak dari ingatan tantenya itu, tetapi ia cukup diuntungkan dengan raut muka Maya yang tampak lebih tenang dari sebelumnya.
“Tante kira anak kamu,” Maya tertawa sembari memukul lengan Rakha yang terseyum getir. “Jadi, kamu dateng sama temenmu itu?”
Rakha hanya cengengesan sembari menggeleng dan berkata, “Panjang ceritanya Tan.”
***
Samara tak seharusnya berada di Stasiun Bogor di jam pulang kantor yang padat merayap seperti sekarang. Jika bukan karena seorang pria bernama Ritzyan Seftian, sulit baginya menerima kuliah dua menit Adit selaku redaksi pelaksana. Jika tak ada hal penting-penting sekali, wanita yang kerap disapa “Sam” itu lebih memilih duduk di kubikelnya sembari streaming drama daripada harus bergumul dengan banyak orang di jam pulang kerja.
Namun untuk urusan Ritz, Samara tidak pernah bisa mangkir. Pria yang sudah dikenalnya selama 12 tahun itu merupakan bagian paling penting dalam hidupnya.
Di tengah lalu-lalang penumpang yang melaju cepat, Samara berusaha menemukan Ritz, sampai beberapa menit hingga dia akhirnya menyerah dan memilih duduk di salah satu bangku sembari mengirim pesan pada Ritz.
Alih-alih menulis pesan, Samara menemukan panggilan tak terjawab dari ibunya. Sudah belasan menit lalu sehingga ia merasa wajib untuk menelepon balik.
“Tumben hari gini sudah balik?” tanya ibunya di seberang telepon.
Samara hanya menjawab sekadarnya sebab jika sudah ditelepon sang ibunda, topik selanjutnya tak akan jauh-jauh dari masalah jodoh.
“Sudah seperempat abad lho, Kak. Mau menunggu sampai kapan?”
Samara jadi kesal. Meskipun ia bisa mengerti bagaimana posisi ibunya yang kerap melihat pernikahan anak tetangga yang usianya bahkan lebih muda, tetap saja topik itu selalu enggan dibahasnya.
“Udah ya, Mom! Ada telepon nih dari kantor, kayaknya penting.” Ini adalah jurus kesekian Samara untuk memutus hubungan telepon dengan ibunya yang tinggal jauh darinya.
“Tante… Sam boong, tuh, enggak ada yang tel—“
“Sudah ditutup…!” Samara merasa menang dari Ritz yang baru saja datang dan berusaha memprovokasi ibunya.
Ritz memasang wajah jenaka dengan melebarkan mulutnya, seolah Samara adalah orang yang paling membosankan.
“Why, are you bored?” Samara menggamit tangan Ritz dengan santai dan membawanya berjalan ke arah yang dia inginkan. “Lu harus traktir gue karena lu bikin gue nunggu tadi.”
Jangan salah paham dulu. Samara dan Ritz tidak berkencan. Mereka hanya bersahabat baik. Ya, meskipun ribuan orang telah melihat hubungan mereka lebih dari sahabat, tetapi pada kenyataannya mereka hanya bersahabat.
Persahabatan antara dua orang yang berlawanan jenis memang terdengar omong kosong. Paling tidak, salah satu dari mereka menyembunyikan perasaan lebih dari sahabat. Kebanyakan kasus memang seperti itu dan Samara termasuk salah satunya. Namun sayangnya, Ritz tak pernah bisa melihat Samara sebagai seorang wanita.
Memang sememilukan itu bagi Samara.
“Boleh-boleh aja, asal lu mau terima seribu jitakan gue,” Ritz bergerak cepat, mengunci kepala Samara dan menjitaknya berulang kali.
Kedua tangan Samara menggapai-gapai kepala Ritz, berusaha untuk balik menyerang, tetapi karena tinggi badannya yang hanya 158 cm tidak cukup menandingi Ritz yang setinggi 178 cm, Samara terpaksa harus mengganti sasarannya, yakni perut Ritz.
“Aak!”
Seketika perkelahian ringan mereka tampak seperti perkelahian dua anak kecil yang sedang berebut mainan. Untungnya hal tersebut tak berlangsung lama mengingat betapa ramainya stasiun itu. Kini keduanya sibuk memilih outlet makanan mana yang akan dijadikan tempat mereka untuk sekadar nongkrong dan ngobrol ngalor-ngidul dengan nyaman.
Pilihan mereka akhirnya jatuh pada outlet ayam goreng terkemuka yang bisa menjadi tempat mereka bercengkrama selama berjam-jam. Dengan paket bucket 6 porsi, mereka memang selapar itu, Samara dan Ritz duduk di sudut outlet.
Baru mencuil ayam, tiba-tiba Ritz merasa kaki kanannya ditendang Samara. Ia refleks mendongak dan melihat Samara menggerak-gerakkan wajahnya sebagai isyarat untuk melihat ke arah yang sama dengan yang dilihat Samara.
“Terus?” Ritz tidak tahu harus bagaimana merespons sepasang kekasih yang duduk tepat di sebelah mereka, yang terlihat saling menyerang dengan kecupan.
Itu memang pemandangan yang cukup umum di ruangan seperti itu, seharusnya Sam terbiasa dan membiarkannya, tetapi jiwa isengnya meronta-ronta.
“Aigu…,” bahkan sampai harus meniru seruan drama Korea langganannya, “pacarku ini ganteng banget kalau lagi makan, ya,” celotehnya sembari mencubit kedua pipi Ritz gemas.
Bak gayung bersambut, Ritz juga bertingkah aneh dengan mencubit kedua pipi Samara dan mengatakan, “Unch unch… jadi kamu makin sayang, kan, sama aku?” lantas mengusap kepala Samara.
Pasangan di samping mereka melihat dengan pandangan terganggu, dan hal itu membuat keduanya semakin senang. Keduanya terus melancarkan aksi sayang-sayangan menjijikkan sampai pasangan yang memang ingin mereka usir karena terlihat tidak sopan di tempat umum itu pergi dengan muka masam. Keduanya lantas terkekeh karena melakukan misi dengan baik.
“Makanya, jangan ngebucin di tempat umum,” ejek Samara yang belum mengalihkan pandangannya dari punggung pasangan tadi.
“Omong-omong, gue jadi inget sesuatu. Kira-kira setuju kan kalau gue lamar Yossi dalam waktu dekat?”
Air muka Samara mendadak tegang. Waktu pun seakan berhenti.
“Lamar?” Samara menelan ludah, getir sekali rasanya. Ia sungguh tidak pernah mempersiapkan diri untuk hal semacam ini dalam hidupnya.
***