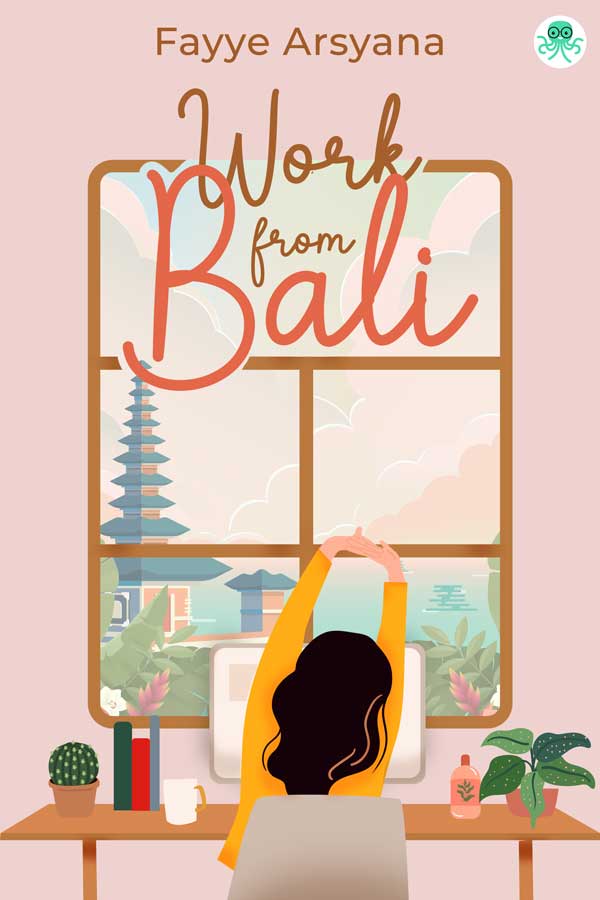
Work from Bali
By Fayye_Arsyana
PROLOG
Pernahkah kamu merasa hidup adalah satu rutinitas panjang yang tak pernah usai? Dalam dua puluh empat jam sehari, hanya hal-hal itu saja yang kamu lakukan. Sangatlah jarang ada hal baru yang bisa kamu dapatkan setiap hari. Kalaupun ada, tidak lama kemudian hal baru itu menjadi bagian dari rutinitasmu. Bosan.
Pernahkah kamu berada dalam satu senyap yang menyesakkan? Hening yang membuatmu berusaha mengisinya dengan berbagai suara lain, hanya demi membuatmu nyaman. Padahal, mungkin itu bukanlah suara yang ingin kamu dengar. Semua ini hanyalah suara pengganti untuk membantumu melewati hening yang tidak kamu suka ini. Sepi.
Malam telah larut. Rumah mungil dengan dua kamar tidur ini tampak sepi. Semua penghuni rumah sudah berada di kamarnya masing-masing. Samar, terdengar suara percakapan dari kamar tidur utama. Bukan, itu bukanlah percakapan dari dua manusia dewasa yang masih terjaga di kamar. Itu adalah percakapan palsu, berasal dari dunia kecil di layar ponsel yang menjadi peneman setia mereka.
Suara di dunia nyata hanyalah dengkur halus seorang bocah perempuan. Tidur begitu lelap di antara lelaki dan perempuan yang sama-sama bergelung di tempat tidur, saling memunggungi, dan sibuk dengan dunia di layar ponsel masing-masing.
Malam demi malam. Hari demi hari. Begitu dekat, tapi begitu jauh.
***
1
“Dev, kita ke Bali, yuk?” ajak Ara pada sang suami yang juga tengah asyik bermain ponsel tidak jauh dari dirinya. “Ternyata banyak temen-temenku yang liburan atau malah pindah sementara ke Bali.”
Ara kembalil memandang foto yang terpampang di ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa senang melihat mereka yang ada di foto itu tampak bahagia dan menikmati liburannya. Ada rasa sedih sekaligus iri karena bukan dirinya yang ada di foto itu. Ada pula rasa takut memikirkan rsiko yang ditempuh demi mendapatkan foto seperti itu. Hanya saja, mereka tampak bahagia.
“Hm, lalu kamu mau ikut-ikutan?” Dev balik bertanya dengan nada kurang suka. “Pergi ke Bali itu berarti harus naik pesawat, berarti kita duduk dempet-dempetan dengan orang lain selama sekitar dua jam. Kalau aku sih malas, ya.”
Maklum saja, berpergian dengan pesawat terbang berarti berada minimal satu jam di sebuah ruang tertutup penuh pendingin udara dan kursi saling berdempetan, sehingga memiliki resiko yang sangat tinggi untuk penyebaran virus COVID-19.
Ara menahan dirinya untuk tidak terbawa emosi mendengar jawaban Dev. Baru juga sekadar bertanya, sudah langsung ditolak. Masih belum mau menyerah, Ara kembali berkata, “Tapi, banyak teman-temanku yang baik-baik saja habis liburan.”
Dev melirik ke arah Ara dan bertanya dengan nada datar. “Kamu tahu apa itu bias kognitif?”
Bola mata Ara berputar ke atas sesaat. Bukannya menanggapi pertanyaan Ara, kenapa malah jadi ada kuis dadakan? Dengan nada sinis, Ara menjawab, “Nggak, aku nggak sepintar dan serajin kamu baca berita.”
Dev langsung duduk lebih tegak dan menggeser tubuhnya sehingga dirinya bisa lebih menghadap Ara. Hal yang sebenarnya agak sulit dilakukan, mengingat ada Kay, anak mereka berdua, yang tertidur pulas di antara mereka. Dengan penuh nada menggurui, Dev berkata, “Jadi, bias kognitif itu adalah kesalahan berpikir yang membuat kita mengambil keputusan yang salah.”
Ara menggigit bibir bawahnya. Malas sebenarnya mendengarkan hal seberat ini menjelang tidur. Pertanyaan Ara sangatlah sederhana, menanyakan pendapat Dev tentang Bali. Kenapa jadi sepanjang dan seberliku ini jawabannya? Mengetahui sifat Dev, pastilah masih banyak penjelasan mengenai bias apalah itu tadi yang hendak diceritakannya.
“Bias kognitif itu makin banyak loh, apalagi di saat seperti ini. Soalnya, kadang kesalahan berpikir itu didukung oleh media, sehingga makin banyak yang ikut-ikutan jadi sesat.”
“Maksud kamu, jadi ikutan aliran kepercayaan sesat?” tanya Ara heran, apa hubungannya aliran sesat dengan pandemi?
Dev menatap Ara dengan serius. “Duh, kamu ini malah bercanda. Aku lagi serius, nih!”
Ara hanya tersenyum miring dan mengangkat sebelah bahunya. “Sudah tengah malam, otakku sudah nggak bisa mikir serius. Lagian, kamu malam-malam malah ceramah.”
Dev memutar bola matanya, tapi kembali meneruskan perkataannya. “Gini, deh. Kamu sering dengar kalau di musim pandemi, imun kuat itu penting banget?”
Kepala Ara mengangguk pelan. Imunitas adalah tameng untuk bertahan di musim seperti ini. Banyak cara untuk mendapatkan imun kuat, entah dari meminum vitamin dan suplemen, minum herbal, berjemur matahari pagi, dan lain sebagainya.
“Lalu, kamu juga sering dengar kalau supaya imun kita kuat, kita harus bahagia. Kalau kita bahagia, maka hormon bahagia di tubuh kita pun meningkat.” Dev mengangkat tangannya dan mulai menghitung dengan jarinya. “Dopamin, Serotonin, Oksitosin, dan dan Endorpin.”
“Iya, aku tahu. Aku nggak sebego itu,” tukas Ara kesal. Setidaknya, untuk hal itu saja dia tahu. Itu pun karena banyak postingan tentang hal tersebut berseliweran di lini masa Instagram.
“Gara-gara prinsip harus bahagia supaya imun kuat, banyak yang melakukan segala sesuatu atas nama membahagiakan diri, misalnya dengan pergi liburan. Kan kalau liburan, hati pasti senang dan bahagia, terus imun jadi lebih kuat, deh. Belum lagi sekarang ada istilah healing atau apalah itu yang aku nggak ngerti maksudnya apa. Liburan ke Bali selalu dibilangnya healing. Liburan ya liburan saja, kenapa sekarang jadi banyak istilah aneh-aneh. Mau liburan kek, mau healing kek, atau mau mudik sekalipun, semua perjalanan jarak jauh punya risiko tinggi tertular virus.”
“Bentar, aku jadi makin bingung,” ujar Ara. “Tadi kita bahas bias apalah itu. Kenapa sekarang jadi bahas healing? Memangnya healing ini contoh bias?”
“Eh, iya. Aku kebablasan.” Dev meringis malu. “Healing bukan bias kognitif, tapi prinsip harus bahagia biar imun kuat, itu bias kognitif. Aku heran, deh. Semua orang ingin pandemi cepat berlalu, tapi kok susah banget patuh protokol kesehatan dan diam di rumah? Malah pada keluyuran dengan alasan biar bahagia dan memperkuat imun. Mau kapan selesainya pandemi ini?”
Ara mendesah sebal. Panjang-panjang begini penjelasannya hanyalah untuk membuktikan bahwa liburan tidak baik dan berisiko tinggi. Ara jadi sedikit menyesal bertanya. Lebih baik dirinya menggunakan waktu yang terpakai mendengarkan ceramah Dev untuk menonton satu episode drama Korea lagi.
“Aku jadi ingat contoh bias kognitif yang lain.” Dev kembali meneruskan penjelasannya, sementara Ara sudah ingin menutup muka dengan bantal. “Ingin ikut-ikutan. Melihat orang lain liburan jadi ingin liburan juga. Takut merasa ketinggalan. FOMO alias Fear of Missing Out.”
Lama-kelamaan, kuping Ara menjadi panas juga mendengar Dev. “Iya, iya. Kalau kamu nggak setuju, ya udah. Nggak usah ceramah panjang lebar begitu. Kita nggak usah ke Bali, nggak usah ke mana pun. Diam aja terus di rumah sampai kiamat.”
Dengan kesal, Ara meletakkan ponsel di nakas dan berbaring sembari memunggungi Dev. Hatinya sangat kesal. Dev bahkan tidak bertanya apa alasan Ara menanyakan pertanyaan itu. Ara tahu bahwa diam di rumah saja adalah hal paling aman yang bisa dilakukannya. Ara bersyukur kantornya dan kantor Dev, mengizinkan karyawan bekerja dari rumah secara penuh. Terakhir kali Ara menginjak lantai gedung kantornya adalah bulan Maret 2020. Ara sampai sudah lupa seperti apa rasanya bekerja penuh waktu di kantor.
“Kenapa kamu ingin ke Bali?” Dev sepertinya bisa membaca kekesalan Ara. “Kenapa sekarang? Bukannya kita juga cukup sering pergi ke Bali sebelum pandemi?”
Tanpa membalikkan badan, Ara menjawab, “Aku kan orang yang FOMO. Ingin seperti teman-teman lain. Liburan, lihat pantai, foto cantik sama keluarganya. Aku pengen bahagia biar imunku kuat.”
Embusan napas Dev terdengar begitu keras di keheningan kamar. “Kenapa kamu malah ngambek?” Ara tidak mau menjawab pertanyaan retorik Dev itu. Dirinya memilih bungkam seribu bahasa. Hening pun kembali merajai.
“Ara,” panggil Dev pelan setelah mereka saling diam beberapa saat. “Aku nggak bilang kalau kamu itu FOMO. Aku tadi cuma berusaha merasionalisasi kenapa sekarang banyak orang yang ngotot liburan, padahal pandemi belum berakhir. Aku ingin tahu, apakah kamu juga seperti itu ataukah ada alasan lain.”
“Memangnya kenapa kalau aku seperti mereka? Aku tuh bosen banget di rumah terus!” tukas Ara sedikit keras. Hatinya kesal karena Dev selalu saja berusaha merasionalkan segala sesuatu. “Iya, aku tahu alasan ini klise banget. Aku harusnya bersyukur masih punya rumah, punya kerjaan, bisa kerja di rumah, masih sehat. Cuma rasanya aku capek banget di rumah terus, sementaa—”
“Sementara banyak temen-temen kamu atau para artis bebas berlibur ke mana-mana dan masih sehat? Apalagi setelah banyak kelonggaran peraturan pelaku perjalanan, banyak yang berkeliaran liburan di luar negeri atau tempat populer semacam Bali itu?” potong Dev cepat. “Aku ngerti kamu bosen, tapi ini kan demi kebaikan kita juga.”
Tidak tahan lagi, Ara membalikkan badan menghadap Dev yang masih dalam posisi duduk. “Dev, aku ke swalayan aja jarang. Kamu terus yang pergi belanja.” Ara menggelengkan kepala. “Jangankan swalayan, ke minimarket depan kompleks aja aku jarang banget. Rasanya lama banget aku nggak lihat dunia luar. Di rumah cuma tidur, makan, ngurus anak, kerja, makan, tidur. Bosan!”
Dev tertawa kecil. “Ngurus anak? Bukannya kamu kerja mulu, makanya Kay lebih sering diasuh Ibu?” Ibu yang Dev sebut ini adalah ibu dari Ara, yang tinggal bersama mereka di Jakarta sejak kelahiran Kay empat tahun lalu. Ayah Ara dan kedua orang tua Dev sudah meninggal sebelum mereka menikah, sehingga hanya tinggal ibu yang berperan sebagai orang tua bagi mereka berdua.
“Jangan mengalihkan topik pembicaraan, deh,” sergah Ara cepat. “Kamu juga kerja terus. Pagi-pagi udah di kamar kerja, cuma keluar pas makan siang sama makan malam. Kita sama aja, tahu!”
“Oke, oke, point taken.” Kedua tangan Dev terangkat tanda menyerah. Mau bagaimanapun juga, mereka memang terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Semua itu berdampak mereka lebih banyak menyerahkan urusan mengasuh Kay dan keseharian rumah tangga pada Ibu.
“Aku juga ngerasa sejak pandemi, kita berdua jadi jauh banget.” Ara bergantian menunjuk dirinya dan Dev. “Padahal kita 24 jam bareng, tapi malah rasanya lebih jauh dari sebelumnya.”
Kening Dev berkerut dan wajahnya menunjukkan kebingungan. “Jauh gimana? Kita bukannya selalu dekat? Tidur aja sekamar, satu ranjang malah! Kalau dulu, iya kadang kerasa jauh, soalnya kamu sering banget dinas ke luar kota.”
“Ih, kalau urusan bias apalah tadi itu aja kamu langsung ceramah.” Ara gemas mendengar perkataan Dev yang menurutnya tidak nyambung. “Giliran ngomongin perasaan, pura-pura bego.”
Dev terkekeh geli melihat Ara yang sewot. “Habisnya kamu ada-ada aja. Aku nggak ngerasa kita jadi jauh. Sama saja seperti dulu.” Dev tampak berpikir sejenak. “Kita sudah hampir lima tahun menikah. Iya sih, nggak lama setelah kita nikah, kamu udah hamil.”
Dev mengetuk-ngetukkan jarinya di dagu. “Jangan-jangan, kamu yang bosan sama aku dan akhirnya ngerasa jauh? Buatku, kita baik-baik saja, sih.”
Lagi-lagi Ara menggigit bibir bawahnya, hal yang biasa dilakukannya saat frustasi tapi bingung hendak bagaimana. Menjabarkan perasaannya pada Dev ternyata tidak segampang yang dibayangkan. Apalagi saat Dev tampak agak meremehkan dan merasa tidak ada masalah seperti itu. Semua baik-baik saja bagi Dev, tapi tidak begitu bagi Ara.
***